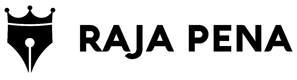Dalam beberapa penggalan edukasi terkait kesehatan mental, kita sering menemukan anjuran untuk memvalidasi emosi. Seseorang dipersilakan untuk mengakui perasaan marah, sedih, kecewa, atau takut sebagai sesuatu yang wajar dan manusiawi.
Psikologi modern menekankan bahwa kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri merupakan langkah awal untuk mengelola emosi itu sendiri. Dengan mengakui bahwa kita sedang marah atau terluka, kita sebenarnya sedang membantu tubuh tetap terkendali agar tidak meledak dan terkuasai oleh emosi tersebut secara berlebihan.
Namun demikian, ada juga nasihat keagamaan yang terdengar seperti batasan terhadap emosi. Ada yang mengatakan bahwa orang beriman tidak sepatutnya marah, bahwa emosi mirip dengan hawa nafsu yang harus ditekan sedemikian rupa agar tidak menodai kesucian hati.
Kalimat-kalimat seperti “jangan marah, bagimu surga”[1] sering dipahami seolah-olah Islam meminta manusia mematikan reaksi emosionalnya. Sebagian orang memandang bahwa psikologi modern dan Islam berada di dua sisi yang tidak sejalan: yang satu mengajak menerima emosi, yang lain seolah meminta menekan emosi. Maka muncul pertanyaan: apakah Islam sebenarnya bertentangan dengan psikologi modern dan apakah agama tidak memberi ruang bagi manusia untuk memvalidasi emosi mereka sendiri?
Emosi sebagai Bagian dari Kemanusiaan
Untuk memahami hubungan Islam dan validasi emosi, kita perlu menyadari terlebih dahulu apa itu emosi. Setiap manusia hidup dengan rangkaian perasaan yang berubah-ubah. Kita marah ketika diperlakukan tidak adil, sedih ketika kehilangan, takut ketika terancam, bahagia ketika menerima kabar baik, atau bimbang ketika dihadapkan pada pilihan sulit.
Bahkan, ada perasaan rumit yang sulit diberi nama; sebuah campuran antara harap dan cemas, antara lega dan hampa, antara rindu dan kesal. Semua kompleksitas ini adalah bagian dari pengalaman hidup manusia. Al-Qur’an tidak sekali pun menyiratkan bahwa manusia harus steril dari emosi. Justru, ia menggambarkan manusia sebagai makhluk yang hidup dengan dinamika rasa.
Dalam kacamata Islam, manusia memang diciptakan dengan sifat thabi’i, yaitu sifat alami bawaan yang mencakup kemampuan merasakan berbagai emosi. Al-Qur’an tidak pernah menggambarkan manusia sebagai makhluk yang tidak boleh menangis, tidak boleh marah, atau tidak boleh takut. Sebaliknya, Al-Qur’an justru berkali-kali menampilkan tokoh-tokoh beriman yang mengalami pergolakan batin.
Nabi Ya’qub as. digambarkan menangis hingga matanya memutih karena kesedihan mendalam ketika kehilangan Nabi Yusuf as. Nabi Yunus as. dilukiskan merasa terhimpit dan putus asa ketika di dalam perut ikan. Bahkan Rasulullah saw sendiri menangis ketika putranya wafat; dan ketika para sahabat keheranan melihat air mata beliau, Rasulullah menegaskan bahwa air mata adalah bagian dari rahmat.[2]
Pemahaman tentang sifat alami ini dijelaskan lebih dalam dalam buku Filsafat Ajaran Islam karya Hadhrat Masih Mau’ud a.s. Di sana diterangkan bahwa manusia memiliki tingkatan-tingkatan nafsu.
Tingkatan yang paling rendah adalah nafsu amarah (ammarah), yaitu kondisi ketika seseorang masih sangat dikuasai dorongan-dorongan emosionalnya. Namun penting digarisbawahi: nafsu amarah bukanlah “kesalahan bawaan”, melainkan tingkatan alami di mana manusia memulai perjalanan spiritualnya. Ia menunjukkan bahwa manusia memang memiliki sifat emosional seperti halnya makhluk lain.
Di titik ini, Islam mengakui bahwa marah, takut, atau sedih adalah bagian dari desain penciptaan. Yang membedakan manusia dari hewan bukan ada atau tidaknya emosi—karena hewan pun bisa marah, takut, dan berduka—melainkan kemampuan manusia untuk menggunakan kesadaran guna mengarahkan emosinya.
Penggambaran-penggambaran ini menunjukkan bahwa manusia mulia dengan derajat keimanan yang tinggi pun bisa dan pernah merasakan hingga meluapkan perasaannya. Pendek kata, luapan emosi bukanlah tanda seseorang jauh dari doa.
Menangis bukan kelemahan. Merasa marah bukan dosa. Bahkan rasa takut pun bukan aib. Yang penting bukan ada atau tidaknya emosi tersebut, tetapi bagaimana seorang manusia menempatkannya, memahami sebab di baliknya, dan mengarahkannya agar tidak membawa pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Dalam ilmu psikologi, emosi dipahami sebagai sinyal alami tubuh. Ia muncul sebagai respons terhadap situasi tertentu, dipengaruhi oleh hormon, cara kita menafsirkan peristiwa, dan pengalaman hidup sebelumnya.
Marah, misalnya, bisa muncul karena kita merasa harga diri dilanggar atau tubuh sedang kelelahan. Sedih dapat menjadi tanda bahwa kita membutuhkan istirahat atau dukungan. Takut bisa membantu kita berhati-hati dan tidak gegabah.
Dengan kata lain, emosi bukan semata-mata sesuatu yang harus dihindari, melainkan pesan dari tubuh dan pikiran yang mengajak kita untuk memperhatikan diri sendiri.
Pengendalian Emosi sebagai Sikap Kesadaran (Mindfulness)
Kesalahpahaman sering muncul ketika nasihat agama dipahami secara literal tanpa melihat konteksnya. Hadis “jangan marah” adalah contoh paling populer. Banyak orang mengira bahwa hadis itu melarang seseorang memiliki emosi marah.
Padahal, para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maksud hadis itu adalah larangan untuk mengikuti dorongan marah sehingga seseorang kehilangan kendali. Artinya, Rasulullah tidak mengatakan “jangan merasa marah,” tetapi “jangan biarkan marah menguasaimu.”
Imam Abu Hamid al-Ghazali memberikan penjelasan tentang potensi marah dalam dua klasifikasi, yaitu at-tafrith (التفريط) dan al-ifrath (الإفراط). At-tafrith adalah kondisi ketika seseorang seharusnya marah tetapi malah tidak meluapkannya. Hal ini digambarkan dalam perkataan Imam as-Syafi’i: “Barangsiapa yang dibuat marah namun tidak marah maka ia (seperti) keledai.”[3] Sedangkan,al-ifrath adalah kondisi ketika potensi marah tidak terkontrol hingga seseorang tidak lagi mampu melihat, berpikir, dan menentukan tindakannya secara jernih.
Rasulullah saw. sendiri pernah mengekspresikan kemarahan ketika prinsip keadilan dilanggar atau ketika seseorang dizalimi. Namun kemarahan beliau tidak pernah berubah menjadi tindakan kasar. Marahnya terarah, proporsional, dan justru menunjukkan keberpihakan terhadap nilai moral.
Ini menjadi bukti bahwa Islam tidak melarang marah sebagai emosi, tetapi membimbing manusia agar marah dengan benar. Dalam psikologi, konsep ini sangat dekat dengan gagasan emotion regulation, yaitu kemampuan untuk merespons emosi dengan cara yang sehat.
Di sisi lain, sebagian orang menafsirkan bahwa kesedihan atau keluh kesah merupakan tanda kurang bersyukur. Padahal Al-Qur’an tidak pernah menuntut manusia untuk selalu tampak kuat. Kesedihan yang diungkapkan Nabi Ya’qub as. tidak pernah dicela oleh Allah. Bahkan doa-doa dalam Al-Qur’an banyak berisi ungkapan batin yang sangat jujur dan rapuh.
Manusia diperintahkan untuk bersabar, tetapi kesabaran yang dimaksud bukan menelan emosi mentah-mentah. Sabar justru adalah kemampuan untuk tetap dalam kendali, meski hati sedang goncang.
Kesalahpahaman yang mengharuskan seseorang menolak emosi justru dapat membuat individu merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi. Ia merasa harus selalu tersenyum agar tampak bersyukur. Ia menahan marah meski sedang diperlakukan tidak adil. Ia menekan kesedihan meski hatinya sedang terluka.
Lama-kelamaan, penolakan emosi ini menciptakan tekanan batin yang berbahaya. Tubuh menyimpan emosi yang ditekan sebagai stres fisiologis. Perasaan-perasaan yang disembunyikan bisa muncul dalam bentuk ledakan yang tak terduga. Dan hubungan antarmanusia sering kali menjadi renggang karena tidak ada kejujuran emosional yang sehat.
Islam tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Islam adalah agama yang manusiawi, bukan agama yang menuntut manusia menjadi malaikat tanpa rasa.
Di sinilah relevansi ajaran Filsafat Ajaran Islam muncul dengan sangat indah. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa perjalanan spiritual manusia adalah perjalanan pengendalian diri dengan penuh kesadaran. Kesadaran inilah yang membuat seseorang naik dari nafsu amarah menuju nafsu lawwamah, hingga mencapai tingkat nafsu mutmainnah yang dipenuhi kedamaian.
Pengendalian ini bukan berbentuk penekanan atau penyangkalan, tetapi pengelolaan yang lahir dari pemahaman tentang kondisi diri. Inilah yang dalam psikologi disebut mindfulness—kemampuan untuk hadir, sadar, dan mengenali perasaan atau pikiran tanpa langsung bereaksi impulsif.
Ketika seseorang berkata kepada dirinya sendiri, “Aku sedang marah, tetapi aku memilih diam sejenak,” ia sedang mempraktikkan pengendalian diri. Ketika ia berkata, “Aku sedang sedih, dan aku membutuhkan waktu untuk memproses ini,” ia sedang mempraktikkan kesadaran. Ketika seseorang berkata, “Ada rasa takut dalam diriku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menuntunku kepada keputusan yang salah,” ia sedang berjalan pada jalan yang diajarkan agama. Dalam tradisi Islam, kesadaran ini sangat dijunjung tinggi. Rasulullah mengajarkan teknik-teknik praktis yang sekarang dipahami dalam psikologi sebagai bentuk grounding atau “menurunkan intensitas emosi.” Beliau mengajarkan untuk berwudu saat marah, diam ketika emosi meninggi, mengubah posisi tubuh, atau menjauh sejenak dari situasi pemicu. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat memahami proses pengelolaan emosi—bukan penolakannya.
Validasi Emosi: Jembatan Islam dan Psikologi
Selain aspek pengendalian, ada satu aspek penting lain yang perlu dipahami: tidak semua masalah emosional bisa ditangani dengan kekuatan diri semata. Ada kalanya, seseorang memerlukan pendampingan profesional.
Hazrat Khalifatul Masih V atba dalam berbagai mulaqat menegaskan bahwa jika seseorang mengalami kesulitan emosional atau psikologis yang cukup berat, maka ia boleh—bahkan dianjurkan—untuk menemui psikolog atau psikiater.
Huzur menjelaskan bahwa Allah menyediakan berbagai jalan pengobatan, dan ilmu psikologi adalah salah satu bentuk rahmat dan karunia yang diberikan kepada manusia untuk saling membantu. Mendatangi psikolog tidak bertentangan dengan tawakal, sama seperti pergi ke dokter ketika tubuh sakit tidak bertentangan dengan iman.
Pernyataan ini sangat penting, karena mematahkan anggapan bahwa “kalau iman kuat, tidak perlu konsultasi.” Justru, iman yang matang adalah iman yang mengambil setiap ikhtiar yang Allah sediakan. Penyembuhan emosional tidak harus dilakukan sendiri. Kita boleh meminta bantuan. Kita boleh mencari bimbingan profesional untuk memahami trauma, kecemasan, atau depresi yang tidak dapat diatasi dengan nasihat umum.
Sarana-sarana rohani seperti memperbanyak doa (shalat), zikir, atau membaca Al-Quran adalah salah satu metode yang bisa membantu meringankan hingga menenangkan. Namun, penulis tidak sepakat jika dikatakan bahwa sarana rohani itu adalah satu-satunya, atau pendapat bahwa mendahulukan penanganann profesional adalah bertentangan dengan ajaran Islam sehingga harus mutlak dihindari.
Jika psikologi dianggap bertentangan dengan agama, tentu seorang Khalifah tidak akan pernah menganjurkan umat untuk mencari psikolog. Tetapi ketika seorang Khalifah mengatakan hal itu, berarti Islam tidak menghalangi, melainkan merangkul pendekatan kesehatan mental yang ilmiah dan profesional.
Salut kepada individu yang baginya doa-doa dan zikir sudah menjadi “mode default” ketika terpantik emosinya, tanpa juga harus menilai para klien psikolog atau pasien psikiater sebagai “golongan lapis bawah” secara keimanan.
Konsep validasi emosi dalam psikologi sebenarnya sangat dekat dengan ajaran Islam. Keduanya beriringan. Validasi tidak berarti membenarkan semua yang kita rasakan atau semua tindakan yang muncul akibat emosi. Validasi berarti mengakui bahwa emosi itu ada, memahami bahwa ia muncul karena sebuah sebab, dan memberi ruang agar emosi tersebut dapat diproses dengan sehat.
Rasulullah saw. memberi contoh nyata. Ketika seseorang datang dalam keadaan marah, beliau tidak menolak perasaan itu. Beliau membiarkan orang tersebut mengungkapkan kegelisahannya. Kemudian Rasulullah memberikan saran-saran sederhana seperti diam sejenak, berwudu, atau mengubah posisi tubuh.
Di balik saran tersebut ada pemahaman mendalam tentang psikologi manusia: bahwa marah tidak bisa dipaksa hilang, tetapi dapat diredakan secara bertahap. Beliau mengajak seseorang mengambil jarak dari emosinya, memberikan ruang untuk menenangkan diri, sehingga pikiran dapat kembali jernih.
Dalam konteks kesedihan, Rasulullah juga menunjukkan validasi yang lembut. Ketika seorang perempuan menangis di sisi kuburan, beliau mendekatinya dan meminta agar ia bersabar. Namun ketika perempuan itu menolak nasihat tersebut karena tidak menyadari bahwa yang berbicara adalah Rasulullah sendiri, beliau tidak memarahinya.[4]
Beliau saw membiarkan perempuan itu memproses emosinya terlebih dahulu. Setelah perempuan itu mengetahui siapa yang menasihatinya, barulah ia mendatangi Rasulullah untuk meminta maaf. Namun yang menarik adalah, Rasulullah tidak menegur tangisannya, tidak melarang sedihnya, dan tidak mengukur kadar imannya berdasarkan emosinya.
Praktik validasi juga tampak dalam hubungan seorang hamba dengan Allah. Ketika seseorang berdoa dalam keadaan rapuh, ketika ia mengakui bahwa hatinya sempit, pikirannya buntu, atau dirinya sedang lemah, ia sebenarnya sedang memvalidasi emosinya. Ia sedang jujur kepada Tuhannya tentang kondisi batinnya. Allah mempersilakan itu.
Dalam Al-Qur’an, Allah berjanji mendengar keluh kesah hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa keluh kesah bukan tanda kurang iman, tetapi tanda bahwa seseorang mengenal batas dirinya dan mencari pertolongan.
Melalui sudut pandang ini, jelas bahwa Islam tidak hanya sejalan dengan psikologi, tetapi juga memberikan fondasi spiritual bagi praktik validasi emosi. Psikologi memberikan penjelasan ilmiah mengenai mekanisme emosi, sementara Islam memberikan dimensi moral dan spiritual yang membuat pengelolaan emosi menjadi lebih utuh.
Pada akhirnya, pertanyaan apakah Islam mengizinkan kita memvalidasi emosi dapat dijawab dengan tegas: bukan hanya mengizinkan, tetapi juga mendorongnya. Manusia diciptakan dengan hati yang sensitif, dengan dinamika rasa yang terus berubah. Islam tidak meminta kita menekan semuanya dan berpura-pura tampak kuat. Islam meminta kita memahami emosi, lalu mengarahkannya pada kebaikan sehingga tidak membiarkannya memimpin kita kepada tindakan yang merugikan.
Memvalidasi emosi bukan berarti membiarkan diri larut dalam rasa marah atau sedih tanpa arah, melainkan sebuah bentuk keberanian untuk mengakui apa yang sedang terjadi dalam diri. Ketika seseorang mampu berkata, “Saya marah,” atau “Saya tidak suka,” ia sedang membuka pintu bagi kesadaran yang lebih besar. Ia sedang belajar mendengar tubuh dan jiwanya. Ia sedang melangkah menuju kematangan spiritual yang lebih dalam.
Islam tidak pernah meminta kita menjadi manusia tanpa air mata. Islam mengakui manusia bisa bergetar takut, bisa meledak marah, bisa goyah karena duka, dan juga bisa begitu lembut karena cinta. Yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola semua itu sehingga tetap membawa manfaat.
Dengan memahami semua ini, kita dapat melihat bahwa Islam tidak hanya sejalan dengan psikologi modern, tetapi juga melengkapinya. Keduanya sama-sama mengajak manusia untuk kembali menjadi manusia seutuhnya: makhluk yang bisa merasa, memahami, dan mengarahkan diri dengan kesadaran yang penuh.
Oleh: Rahma A. Roshadi
Referensi:
[1] HR Ath-Thabrani
[2] Sahih Bukhari Muslim
[3] Imam Syafii dikutip Al-Ghazali dalam kitab Ihya` Jilid 3, h. 207
[4] Syarah Riyadhus-Shalihin, bab Ziarah Kubur
Editor: Ammar Ahmad