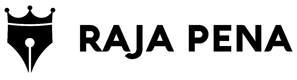Pada masa Rasulullah ﷺ, umat Islam berhimpun dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu Jama’ah Muslimin, yang berlandaskan wahyu Ilahi dan ketaatan mutlak kepada Rasulullah ﷺ sebagai pembawa risalah dan pemimpin rohani sekaligus politik. Sistem ini mencerminkan tatanan kehidupan yang harmonis antara dimensi spiritual dan duniawi, di mana setiap aspek kehidupan umat diatur berdasarkan tuntunan langsung dari Allah melalui wahyu yang diterima oleh Rasulullah ﷺ. Kesatuan ini bukan hanya bersifat formal atau politis, tetapi merupakan ikatan ruhani yang mendalam, yang mengikat setiap individu Muslim dengan sumber kebenaran absolut.
Sistem kepemimpinan profetik ini berlanjut setelah wafatnya Rasulullah ﷺ melalui institusi Khilafah Rasyidah yang dipimpin oleh empat khalifah pertama: Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhum ajma’in. Para khalifah ini melanjutkan model pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip kenabian, yaitu Khilafah ‘ala Minhaajin Nubuwwah — kepemimpinan yang mengikuti metode kenabian. Mereka memimpin dengan syura (musyawarah), keadilan, kesederhanaan, dan pengabdian total kepada Allah dan umat, serta menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.
Rasulullah ﷺ telah memberikan peringatan yang sangat serius mengenai pentingnya menjaga kesatuan jamaah ini. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda:
“Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan (kepada imam/pemimpin) maka ia akan menemui Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujjah (alasan yang sah). Dan barang siapa mati sedang di lehernya tidak ada bai’at (kepada imam), maka ia mati dalam keadaan jahiliah.” (Sahih Muslim 1851a)
Hadis ini menunjukkan bahwa kesatuan jamaah bukan sekadar anjuran, melainkan merupakan pilar fundamental dalam kehidupan beragama seorang Muslim. Melepaskan diri dari jamaah, meskipun hanya sedikit, dapat berakibat pada terputusnya ikatan spiritual dengan Islam itu sendiri. Kesatuan jamaah ini merupakan simbol keterikatan spiritual umat dengan wahyu dan petunjuk Ilahi, sekaligus menjadi manifestasi dari prinsip tauhid yang mengharuskan umat untuk bersatu di bawah satu kepemimpinan yang sah dan direstui oleh Allah.
Selama sistem kenabian dan khilafah berjalan seiring dalam harmoni, Islam tumbuh menjadi kekuatan moral, spiritual, dan intelektual yang dominan di dunia. Umat Islam pada masa itu tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban. Kesatuan yang tercipta di bawah kepemimpinan kenabian dan khilafah rasyidah menjadi fondasi bagi kemajuan luar biasa yang dicapai oleh peradaban Islam pada masa-masa awalnya.
Namun, benih perpecahan mulai muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu. Ekspansi wilayah Islam yang sangat cepat pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan berlanjut pada masa Utsman membawa konsekuensi yang kompleks. Wilayah kekuasaan Islam yang membentang dari Persia di timur hingga Afrika Utara di barat memunculkan tantangan administratif, sosial, dan politik yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Perbedaan pandangan mengenai cara mengelola wilayah yang luas, pembagian harta rampasan perang (ghanimah), pengangkatan gubernur, dan berbagai kebijakan administratif lainnya mulai memicu ketegangan di kalangan umat.
Tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu pada tahun 35 H menjadi titik balik yang sangat krusial dalam sejarah Islam. Pembunuhan terhadap khalifah yang sah ini membuka pintu fitnah besar yang mengguncang fondasi kesatuan umat. Peristiwa ini disusul oleh berbagai konflik internal, termasuk Perang Jamal dan Perang Shiffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, yang memperlihatkan pertarungan antara kelompok-kelompok yang berbeda interpretasi mengenai kepemimpinan yang sah dan cara menyelesaikan permasalahan umat.
Konflik antara Khalifah Ali radhiyallahu ‘anhu dan kelompok yang menentangnya menandai awal dari kemerosotan kesatuan umat yang sebelumnya telah terjaga dengan kokoh. Munculnya kelompok Khawarij yang menganggap diri mereka paling benar dan mengkafirkan kelompok lain, serta perpecahan antara pendukung Ali (yang kelak menjadi cikal bakal Syi’ah) dan pendukung Mu’awiyah (yang menjadi mayoritas Sunni), menciptakan retakan yang semakin dalam di tubuh umat Islam.
Yang sangat menyedihkan adalah bahwa tiga dari empat Khalifah Rasyidin — Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ‘anhum — wafat sebagai syuhada (martir), terbunuh oleh tangan-tangan yang mengaku Muslim.
Hal ini menandakan transisi yang tragis dari sistem kepemimpinan yang murni ruhani dan profetik menjadi sistem yang lebih bersifat politik dan kerajaan (mulkan), di mana kekuasaan lebih sering diperebutkan dengan cara-cara politik dan bahkan kekerasan, bukan lagi semata-mata berdasarkan kedekatan spiritual dan kelayakan moral.
Rasulullah ﷺ telah menubuatkan kondisi ini jauh sebelumnya. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda:
“Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Khilafah dalam umatku akan berlangsung selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu akan muncul pemerintahan kerajaan (monarki).” (Jami` at-Tirmidhi 2226)
Nubuwatan ini terbukti dengan sangat akurat. Masa kepemimpinan empat Khalifah Rasyidin berlangsung kurang lebih tiga puluh tahun: Abu Bakar (dua tahun), Umar (sepuluh tahun), Utsman (dua belas tahun), dan Ali (lima tahun), hingga tahun 40 H. Dengan wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu pada tahun 40 H, Khilafah ‘ala Minhaajin Nubuwwah secara resmi berakhir. Kepemimpinan Islam kemudian beralih kepada sistem kerajaan (mulk) yang dimulai dengan Dinasti Umayyah di bawah Mu’awiyah bin Abi Sufyan.
Sejak saat itu, umat Islam memasuki masa panjang yang ditandai oleh berbagai perpecahan mazhab, aliran teologi, konflik politik, kebekuan spiritual, dan hilangnya otoritas wahyu dalam kepemimpinan Islam. Meskipun dinasti-dinasti Islam yang muncul setelahnya — seperti Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, Utsmaniyah, dan lain-lain — berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, namun kesatuan spiritual dan otoritas kenabian yang menjadi ciri khas masa Khulafaur Rasyidin tidak pernah benar-benar terwujud kembali.
Dalam menghadapi kondisi perpecahan dan kemunduran spiritual yang akan dialami umat Islam di masa depan, Rasulullah ﷺ tidak membiarkan umatnya tanpa harapan. Beliau memberikan kabar gembira (busyra) mengenai akan datangnya seorang pembaru Ilahi yang akan diutus oleh Allah pada masa ketika umat mengalami perselisihan dan kegoncangan besar. Pembaru ini dikenal dengan sebutan Al-Mahdi, yang secara harfiah berarti “yang diberi petunjuk” atau “yang mendapat hidayah”.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
“Ubasysyirukum bil-Mahdī, yub‘atsu fī ummatī ‘alā ikhtilāfin mina an-nāsi wa zalāzila.”
“Aku khabarkan kepada kalian berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku ketika terjadi perselisihan di antara manusia dan kegoncangan-kegoncangan.” (Musnad Aḥmad)
Hadis ini memiliki signifikansi teologis yang sangat mendalam, terutama dari penggunaan kata kerja يُبْعَثُ (yub’athu), yang berasal dari akar kata ب ع ث (ba-‘a-tha) yang berarti “diutus” atau “dibangkitkan”. Dalam terminologi Qur’ani, kata yub’athu dan derivasinya secara konsisten dan eksklusif digunakan untuk merujuk kepada para rasul dan orang-orang yang diutus secara khusus oleh Allah dengan misi ilahi. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Qur’an:
“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: ‘Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku.'” (QS. Al-Anbiya: 25)
Penggunaan istilah yub’athu dalam Hadis tentang Al-Mahdi menunjukkan bahwa kedatangannya bukan sekadar sebagai pemimpin politik atau reformis sosial biasa, melainkan sebagai sosok yang diutus oleh Allah dengan status spiritual yang tinggi. Ini menegaskan bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang mendapat pengutusan Ilahi (mab’uts) dari kalangan umat Muhammad ﷺ.
Namun, perlu dipahami dengan jelas bahwa pengutusan ini tidak berarti beliau adalah nabi dengan syariat baru (nabi tasyri’i) yang membawa hukum-hukum baru yang berbeda dari syariat Muhammad ﷺ. Sebaliknya, beliau adalah seorang nabi bayangan (nabi zilli) atau nabi non-legislatif (nabi ghairu tasyri’i) yang berfungsi untuk memperbaharui dan menghidupkan kembali ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ, serta mempersatukan umat di bawah bimbingan dan bayang-bayang kenabian Muhammad ﷺ.
Konsep nabi zilli ini sangat penting untuk dipahami dalam konteks teologi Islam, terutama dalam kaitannya dengan doktrin Khatam an-Nabiyyin (penutup para nabi). Nabi zilli adalah seseorang yang mencapai tingkat kesempurnaan ruhani yang sangat tinggi melalui ketaatan sempurna kepada Nabi Muhammad ﷺ, sehingga Allah menganugerahkan kepadanya wahyu dan status kenabian sebagai refleksi dari cahaya kenabian Muhammad ﷺ. Beliau tidak membawa syariat baru, tetapi menegakkan dan memperbaharui syariat yang sudah ada.
Hadis tentang Al-Mahdi ini juga menjelaskan konteks kedatangannya, yaitu pada masa “ikhtilaf” (perselisihan) dan “zalazil” (kegoncangan). Kata ikhtilaf menunjuk pada perpecahan internal umat Islam dalam hal akidah, mazhab, pemahaman agama, dan kepemimpinan. Sementara zalazil merujuk pada berbagai kegoncangan, baik dalam bentuk krisis spiritual, moral, intelektual, maupun sosial-politik yang mengguncang fondasi keimanan umat. Kondisi ini sangat tepat menggambarkan keadaan dunia Islam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika umat Islam mengalami perpecahan internal yang parah, kemunduran ilmu pengetahuan, kolonialisme Barat, krisis identitas, dan serangan ideologis dari berbagai arah.
Salah satu pertanyaan teologis yang paling mendasar dan sering menimbulkan kontroversi dalam diskusi tentang kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih Mau’ud adalah: Apakah masih ada kemungkinan munculnya nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, mengingat beliau adalah Khatam an-Nabiyyin (penutup para nabi)?
Untuk menjawab pertanyaan ini dengan komprehensif, kita perlu memahami makna hakiki dari istilah Khatam an-Nabiyyin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Allah berfirman:
“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan Khatam an-Nabiyyin.” (QS. Al-Ahzab: 40)
Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah Khatam an-Nabiyyin. Namun, pertanyaannya adalah: apa makna sebenarnya dari “penutup” (khatam) dalam konteks ini? Apakah ini berarti tidak ada lagi nabi sama sekali setelah beliau, ataukah ini berarti tidak ada nabi yang lebih tinggi derajatnya atau yang membawa syariat baru setelah beliau?
Al-Qur’an sendiri memberikan petunjuk penting dalam ayat lain yang menjelaskan bahwa para nabi memiliki derajat yang berbeda-beda:
“Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 253)
Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah telah melebihkan sebagian nabi atas yang lain dalam hal derajat dan kemuliaan. Dengan demikian, istilah Khatam an-Nabiyyin yang disandang oleh Nabi Muhammad ﷺ harus dipahami dalam konteks ini: setelah Nabi Muhammad ﷺ, tidak ada lagi nabi yang derajatnya sama dengan atau lebih tinggi dari beliau. Beliau adalah penutup para nabi dari segi kemuliaan, kesempurnaan, dan universalitas risalah. Syariat beliau adalah syariat yang sempurna dan abadi, yang akan berlaku hingga hari kiamat.
Namun, ini tidak berarti bahwa pintu kenabian dalam pengertian rohani dan zilli (bayangan) telah tertutup sepenuhnya. Allah masih dapat menganugerahkan status kenabian kepada hamba-hamba-Nya yang mencapai tingkat kesempurnaan dalam ketaatan kepada Nabi Muhammad ﷺ, asalkan kenabian tersebut bersifat subordinat, tidak membawa syariat baru, dan sepenuhnya tunduk kepada syariat Muhammad ﷺ.
Konsep ini dijelaskan dengan sangat indah dalam firman Allah:
“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqin (orang-orang yang sangat membenarkan), para syuhada (para martir), dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (QS. An-Nisa’: 69)
Ayat ini sangat fundamental dalam memahami kontinuitas spiritual dalam Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa melalui ketaatan yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang hamba dapat mencapai derajat-derajat tertinggi dalam kehidupan spiritual, termasuk derajat kenabian (nabiyyin). Allah menyebutkan empat kategori orang yang mendapat nikmat-Nya: para nabi (nabiyyin), para shiddiqin (orang-orang yang sangat membenarkan), para syuhada (para martir), dan orang-orang saleh. Urutan ini menunjukkan hierarki spiritual, dengan kenabian sebagai puncaknya.
Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa ayat ini menggunakan kata kerja masa depan “faulā’ika ma’a” (maka mereka itu akan bersama-sama), yang menunjukkan bahwa janji ini tidak terbatas pada masa lalu, tetapi terus berlaku untuk umat Islam di masa depan. Dengan kata lain, pintu untuk mencapai derajat-derajat spiritual tertinggi, termasuk kenabian, masih terbuka bagi mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan sempurna.
Namun, perlu ditekankan sekali lagi bahwa kenabian yang dimaksud di sini adalah kenabian ghairu tasyri’iyyah (kenabian tanpa membawa syariat baru) atau kenabian zilliyyah (kenabian bayangan), yaitu kenabian yang merupakan manifestasi dan refleksi dari cahaya kenabian Muhammad ﷺ. Orang yang mencapai derajat ini tidak membawa wahyu yang independen atau syariat yang berbeda, melainkan menerima wahyu yang meneguhkan dan menghidupkan kembali syariat Muhammad ﷺ. Beliau adalah nabi dalam pengertian bahwa Allah berkomunikasi dengannya melalui wahyu, tetapi wahyu tersebut sepenuhnya dalam kerangka dan bimbingan kenabian Muhammad ﷺ.
Konsep ini juga dijelaskan dalam Hadis-Hadis Rasulullah ﷺ. Dalam sebuah Hadis yang sahih, Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidak ada kenabian setelahku, kecuali mubashshirat (kabar gembira).”
Ketika ditanya apa itu mubashshirat, beliau menjawab: “Mimpi yang saleh.” (Sahih al-Bukhari 6990)
Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun kenabian dalam pengertian nabi tasyri’i (nabi dengan syariat baru) telah berakhir, namun aspek-aspek tertentu dari kenabian, seperti menerima kabar gembira dari Allah melalui mimpi yang benar atau wahyu dalam pengertian tertentu, masih dapat dialami oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini membuka kemungkinan bagi munculnya individu-individu yang mencapai derajat spiritual yang sangat tinggi, yang dapat disebut sebagai nabi dalam pengertian zilli dan ghairu tasyri’i.
Untuk memahami lebih jauh tentang kontinuitas spiritual dan kemungkinan munculnya nabi zilli dalam umat Islam, kita perlu merenungkan doa yang paling sering dibaca oleh setiap Muslim, yaitu Surah Al-Fatihah. Surah ini dibaca minimal 17 kali sehari dalam shalat wajib, belum termasuk shalat-shalat sunnah. Dalam surah ini, Allah mengajarkan kepada umat Islam untuk berdoa:
“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (QS. Al-Fatihah: 6-7)
Pertanyaan yang sangat penting adalah: Siapakah “orang-orang yang telah dianugerahi nikmat” (alladhina an’amta ‘alaihim) dalam ayat ini? Jawabannya dijelaskan dengan sangat jelas dalam QS. An-Nisa’: 69 yang telah kita bahas sebelumnya: mereka adalah para nabi (nabiyyin), para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh.
Dengan demikian, setiap kali seorang Muslim membaca Al-Fatihah dalam shalatnya, ia sebenarnya sedang memohon kepada Allah agar dibimbing ke jalan para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Ini adalah doa untuk memperoleh hidayah yang sama dengan yang diberikan kepada para nabi, untuk mencapai derajat spiritual yang sama, dan untuk mendapat nikmat yang sama dari Allah.
Apakah masuk akal jika Allah mengajarkan umat-Nya untuk berdoa meminta sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan? Apakah Allah akan memerintahkan kita untuk berdoa agar dibimbing ke jalan para nabi, sementara pintu kenabian telah tertutup rapat selamanya? Tentu tidak. Fakta bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa demikian menunjukkan bahwa nikmat kenabian, dalam pengertian tertentu, masih dapat dianugerahkan kepada umat Muhammad ﷺ.
Doa Al-Fatihah ini bukan sekadar permintaan untuk mengikuti jejak para nabi dalam hal akhlak dan amal saleh saja, tetapi juga permintaan untuk mencapai derajat spiritual yang sama, yaitu kemungkinan untuk menerima wahyu dan bimbingan langsung dari Allah, sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Tentu saja, ini tidak berarti menjadi nabi seperti nabi-nabi sebelum Muhammad ﷺ yang membawa syariat baru, tetapi menjadi nabi dalam pengertian zilli, yang menerima wahyu untuk meneguhkan dan menghidupkan kembali syariat Muhammad ﷺ.
Setelah berabad-abad umat Islam berdoa dengan Al-Fatihah, memohon agar dibimbing ke jalan para nabi dan orang-orang yang mendapat nikmat Allah, dan setelah umat mengalami perpecahan yang sangat parah, kemunduran spiritual, dan krisis keimanan yang mendalam pada abad ke-19, Allah mengabulkan doa tersebut dengan mengutus seorang hamba-Nya yang telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam ketaatan kepada Nabi Muhammad ﷺ.
Pada tahun 1305 H / 1888 M, Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. dari kota Qadian, Punjab, India, sebagai Khalifatullah (wakil Allah di bumi), Al-Mahdi al-Mau’ud (Imam Mahdi yang dijanjikan), dan Al-Masih Mau’ud (Isa yang dijanjikan). Beliau adalah seorang hamba Allah yang telah mencapai maqam fana fillah (fana dalam Allah) dan fana fir-rasul (fana dalam Rasulullah ﷺ), yaitu tingkat spiritual di mana keberadaan individu sepenuhnya larut dalam kehendak Allah dan dalam ketaatan kepada Rasulullah ﷺ.
Pengutusan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba atau tanpa dasar. Beliau mengklaim bahwa pengutusan beliau telah dinubuatkan oleh Rasulullah ﷺ dalam berbagai Hadis tentang kedatangan Al-Mahdi dan Al-Masih Mau’ud. Lebih dari itu, beliau menegaskan bahwa pengutusan beliau adalah pemenuhan janji Allah dalam QS. An-Nisa’: 69 tentang kemungkinan munculnya nabi zilli dalam umat Muhammad ﷺ, dan juga pengabulan doa yang dibaca oleh setiap Muslim dalam Al-Fatihah untuk dibimbing ke jalan para nabi.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. menerima wahyu dari Allah yang meneguhkan status beliau sebagai nabi zilli. Beliau menulis:
“Dalam wahyu Ilahi ini aku disebut dengan kata “rusul” karena di dalam Barahin Ahmadiyyah Allah Ta’ala menetapkan aku sebagai manifestasi seluruh nabi dan menisbahkan nama segenap nabi kepadaku. Aku adalah Adam, Syits, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yaqub, Yusuf, Musa, Daud, Isa ‘alihimussalam dan aku merupakan manifestasi sempurna nama Rasulullah ﷺ, yakni secara bayangan (zilli) aku adalah Muhammad ﷺ dan Ahmad.” (Haqiqatul Wahy, Catatan Kaki nomor 8, Dalam terjemahan Bahasa Indonesia)
Pernyataan ini dengan jelas menunjukkan bahwa klaim kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as adalah kenabian yang sangat berbeda dari kenabian para nabi sebelum Muhammad ﷺ. Beliau tidak mengklaim membawa agama baru, tidak mengklaim sebagai nabi yang lebih tinggi atau setara dengan Nabi Muhammad ﷺ, dan tidak mengklaim bahwa wahyu yang beliau terima menggantikan Al-Qur’an. Sebaliknya, beliau mengklaim sebagai nabi subordinat, nabi bayangan, nabi yang sepenuhnya tergantung pada dan tunduk kepada kenabian Muhammad ﷺ.
Asal-usul spiritual dan legitimasi ruhani Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ‘alaihis-salām mendapat pengakuan dari seorang tokoh sufi besar yang hidup sezaman dengannya, yaitu Khawaja Ghulam Farid dari Chachran Sharif. Khawaja Ghulam Farid adalah seorang mursyid (guru spiritual) terkemuka dari tarekat Chishtiyah di Punjab, India, yang sangat dihormati baik oleh kalangan Sunni maupun Syi’ah. Beliau dikenal sebagai wali yang mencapai maqam spiritual yang sangat tinggi, seorang penyair sufi yang produktif, dan seorang ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf dan hakikat agama.
Dalam karya beliau yang berjudul Ishārāt-e-Farīdī (Isyarat-isyarat Farid), Khawaja Ghulam Farid menulis kesaksian yang sangat bernilai historis dan spiritual tentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.:
“Saya mengetahui bahwa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani adalah orang yang benar dan jujur dalam urusannya. Dia tenggelam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan ia adalah seorang yang penuh pengorbanan dalam usahanya untuk kemajuan Islam dan meninggikan agama. Kami tidak melihat sesuatu pun yang tercela dan buruk dalam keyakinannya. Meskipun ia mengaku sebagai nabi dan sebagai Isa yang dijanjikan, hal itu pun termasuk dalam perkara yang diperbolehkan.”
Kesaksian ini memiliki signifikansi yang sangat mendalam dari beberapa aspek:
- Pertama, kesaksian ini datang dari seorang wali Allah yang telah mencapai maqam spiritual yang tinggi dan memiliki kashf (penyingkapan spiritual). Dalam tradisi tasawuf, para wali yang mencapai maqam tertentu memiliki kemampuan untuk mengenali kebenaran ruhani seseorang melalui penglihatan batiniah mereka. Fakta bahwa Khawaja Ghulam Farid, yang hidup pada masa yang sama dan mengenal Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., memberikan kesaksian positif tentang beliau menunjukkan bahwa dari perspektif tasawuf ortodoks, tidak ada yang cacat atau menyimpang dalam klaim spiritual beliau.
- Kedua, Khawaja Ghulam Farid secara spesifik menyebutkan bahwa meskipun Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. mengklaim sebagai nabi dan sebagai Isa (Yesus) yang dijanjikan, hal tersebut “termasuk dalam perkara yang diperbolehkan” (jā’iz). Ini adalah pernyataan yang sangat penting karena menunjukkan bahwa seorang ulama sufi yang sangat dihormati tidak melihat klaim kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau sebagai pelanggaran terhadap doktrin Khatam an-Nabiyyin. Sebaliknya, beliau memahami bahwa klaim tersebut merujuk pada konsep kenabian zilli yang sah dan diperbolehkan dalam kerangka teologi Islam.
- Ketiga, kesaksian ini menunjukkan bahwa Khawaja Ghulam Farid mengakui ketulusan, kesalehan, dan pengorbanan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. dalam membela dan meninggikan Islam. Beliau menyaksikan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. adalah seorang yang “tenggelam dalam ibadah kepada Allah” dan “penuh pengorbanan dalam usahanya untuk kemajuan Islam”. Ini adalah pengakuan terhadap kualitas spiritual dan dedikasi beliau terhadap agama Islam.
- Keempat, dari perspektif historis, kesaksian ini sangat berharga karena datang dari sumber yang independen dan tidak memihak. Khawaja Ghulam Farid bukanlah pengikut Jama’at Ahmadiyah, dan beliau tidak memiliki kepentingan pribadi dalam memberikan kesaksian ini. Kesaksian beliau adalah murni pengakuan spiritual berdasarkan penglihatan batiniah dan penilaian objektif terhadap karakter dan misi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s..
Kesaksian Khawaja Ghulam Farid ini menegaskan bahwa pengutusan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. bukan hanya diakui oleh para pengikutnya, tetapi juga mendapat pengakuan dari tokoh-tokoh spiritual yang dihormati pada masanya. Ini menambah legitimasi spiritual dan moral dari misi beliau, dan menunjukkan bahwa klaim beliau dapat diterima dalam kerangka tradisi spiritual Islam yang autentik.
Selain Khawaja Ghulam Farid, ada juga beberapa ulama dan tokoh spiritual lainnya pada masa itu yang memberikan testimoni positif atau setidaknya tidak menentang klaim Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.. Ini menunjukkan bahwa pada masa awal, sebelum politisasi dan polarisasi yang terjadi kemudian, beberapa ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf dan hakikat agama dapat melihat kebenaran dalam klaim beliau.
Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang status Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. sebagai nabi zilli, kita perlu mengeksplorasi konsep ini secara lebih komprehensif dari perspektif teologi Islam, khususnya dalam tradisi tasawuf.
Dalam tradisi tasawuf, perjalanan spiritual seorang salik (penempuh jalan spiritual) menuju Allah dibagi dalam beberapa maqamat (kedudukan-kedudukan spiritual) dan ahwal (keadaan-keadaan spiritual). Puncak tertinggi dari perjalanan ini adalah maqam fana fillah (fana dalam Allah) dan baqa billah (kekal bersama Allah). Pada maqam ini, individu mencapai tingkat kesatuan spiritual dengan Tuhan, di mana kehendak pribadinya sepenuhnya larut dalam kehendak Ilahi.
Para sufi besar seperti Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Al-Ghazali telah menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mencapai maqam fana fillah, ia dapat menerima fayd (pancaran) atau tajalli (manifestasi) dari sifat-sifat Ilahi. Dalam kondisi ini, ia dapat mengalami berbagai bentuk komunikasi dengan Allah, termasuk menerima ilham (inspirasi), mukasyafah (penyingkapan), dan bahkan wahyu dalam pengertian tertentu.
Konsep kenabian zilli dibangun di atas fondasi tasawuf ini. Seorang nabi zilli adalah individu yang telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam ketaatan kepada seorang nabi mustaqill (nabi independen dengan syariat), dalam hal ini Nabi Muhammad ﷺ, sehingga ia menjadi cerminan sempurna dari cahaya kenabian nabi tersebut. Dalam bahasa tasawuf, ia telah mencapai maqam fana fir-rasul (fana dalam Rasul), di mana ia kehilangan identitas individualnya dan menjadi bayangan atau refleksi dari Rasulullah ﷺ.
Ketika seseorang mencapai maqam ini, Allah dapat menganugerahkan kepadanya wahyu yang merupakan refleksi dari wahyu yang diterima oleh nabi yang ia ikuti. Wahyu ini tidak bersifat mustaqill (independen) atau tasyri’i (legislatif), tetapi bersifat tabi’i (mengikuti) dan ghairu tasyri’i (non-legislatif). Wahyu yang diterima oleh nabi zilli berfungsi untuk:
1. Meneguhkan dan menguatkan wahyu yang telah ada dalam kitab suci nabi yang ia ikuti (dalam hal ini Al-Qur’an).
2. Memberikan bimbingan spiritual yang spesifik untuk kondisi zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat pada masanya.
3. Menghidupkan kembali ajaran agama yang telah menjadi usang atau terlupakan.
4. Memberikan interpretasi yang otoritatif terhadap wahyu yang telah ada, sesuai dengan kebutuhan zaman.
5. Menyingkap makna-makna tersembunyi (batin) dari kitab suci yang belum terungkap sebelumnya.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. menjelaskan konsep kenabian zilli-nya dengan sangat jelas dalam berbagai tulisan beliau. Beliau menegaskan bahwa:
Beliau ﷺ tidak rela pintu wahyu yang merupakan akar pokok untuk meraih ma’rifat Ilahi dibiarkan tertutup atas mereka. Ya, untuk menghidupkan tanda khatamu risalah (stempel kenabian), keteguhan dan rasa simpati beliau menghendaki supaya keberkatan wahyu dapat diraih dengan cara mengikuti beliau. Bagi orang yang bukan umat beliau ﷺ, pintu wahyu Ilahi tertutup. Dalam makna inilah Tuhan telah menetapkan beliau sebagai Khatamul-Anbiya’.
Jadi, telah ditetapkan hingga Hari Kiamat bahwa orang yang tidak membuktikan dirinya sebagai umatnya yang benar-benar taat, serta tidak memfanakan dirinya secara utuh dalam mengikuti beliau, sekali-kali tidak akan memperoleh wahyu yang sempurna hingga Hari Kiamat, dan ia tidak akan mungkin menjadi mulham (penerima ilham) yang sempurna, sebab kenabian mustaqil (secara langsung) telah berakhir pada wujud Nabi Muhammad ﷺ.
Tetapi kenabian Zhilli yang bermakna memperoleh wahyu hanya melalui keberkatan Nabi Muhammad ﷺ saja, kenabian itu yang akan tetap berlangsung hingga Hari Kiamat, supaya pintu kesempurnaan manusia tidak tertutup hingga Hari Kiamat dan supaya tanda ini tidak terhapus dari dunia bahwa yang dikehendaki oleh tekad Rasulullah ﷺ yaitu agar pintu mukaalamah dan mukhaatabah terus terbuka selamanya dan ma’rifat Ilahi yang merupakan pangkal keselamatan tidak lenyap.
Sekali-kali kalian tidak akan menemukan hadis sahih yang menyatakan bahwa sesudah beliau akan ada lagi nabi yang Ghair Ummati yakni tidak mendapatkan keberkatan karena tidak mengikuti beliau ﷺ sehingga dari sinilah terbukti kekeliruan orang-orang yang tanpa dasar membawa kembali Hazrat Isa a.s. ke dunia dan hakikat akan kedatangan Nabi Ilyas a.s. yang kedua kali terungkap dari penjelasan Hazrat Isa a.s. sendiri. Akan tetapi setelah itu mereka tidak mengambil pelajaran. (Haqīqat al-Wahy, Rūhānī Khazā’in, jilid 18)
Konsep ini sebenarnya tidak asing dalam tradisi Islam. Para ulama sufi seperti Muhyiddin Ibn ‘Arabi telah menulis tentang konsep “Khatm al-Wilayah al-Muhammadiyah” (Penutup Kewalian Muhammadiyah), yaitu seorang wali yang mencapai kesempurnaan tertinggi dalam mengikuti Nabi Muhammad ﷺ dan menjadi manifestasi dari kewalian Muhammadiyah.
Setelah wafatnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. pada tahun 1908, Jama’at Ahmadiyah menghadapi ujian besar: bagaimana mempertahankan kesatuan jamaah dan melanjutkan misi yang telah dimulai? Jawaban atas tantangan ini datang melalui institusi Khilafat Ahmadiyah, yang didirikan pada tahun 1908 dengan terpilihnya Hazrat Maulvi Nuruddin r.a. sebagai Khalifatul Masih I (Khalifah Pertama Al-Masih).
Institusi Khilafat Ahmadiyah adalah manifestasi dari janji Allah dalam QS. An-Nur: 56:
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.” (QS. An-Nur: 56)
Khilafat Ahmadiyah bukan hanya sekadar kepemimpinan administratif atau politik, tetapi merupakan kepemimpinan spiritual yang berlandaskan prinsip-prinsip kenabian, yaitu Khilafah ‘ala Minhaajin Nubuwwah. Khalifah dipilih secara demokratis oleh dewan pemilih dari Jama’at Ahmadiyah, tetapi pemilihan tersebut dipandu oleh doa dan petunjuk dari Allah. Khalifah bukanlah nabi, tetapi beliau adalah wakil (khalifah) dari Al-Masih Mau’ud dan penerus misi beliau.
Melalui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Islam kembali menemukan jiwanya, dan Khilafah ‘ala Minhaajin Nubuwwah tegak kembali sebagai sistem Ilahi yang membimbing dunia menuju kedamaian dan kebenaran.
Oleh: Usamah Ahmad Rachmadi
Referensi:
Sunnah.com — Hadith Collections: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah. https://sunnah.com
The Holy Qur’an (English Translation). Tilford, Surrey: Islam International Publications, 2002.
Friedmann, Yohanan. Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and Its Medieval Background. Berkeley: University of California Press, 1989.
Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia. (2025, 18 Januari). Khilafah ‘alaa Minhaajin Nubuwwah. Ahmadiyah.id. https://ahmadiyah.id/khilafah-alaa-minhaajin-nubuwwah
Al Hakam. (2022, October 7). What is the meaning of ‘Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah’? Alhakam.org. https://www.alhakam.org/what-is-the-meaning-of-khilafah-ala-minhaj-an-nubuwwah/
Al Hakam. (2023, September 29). Prophets of Allah — Prophet Ahmad: The Perfect Follower of Muhammad. Retrieved from https://www.alhakam.org/prophets-of-allah-prophet-ahmad-the-perfect-follower-of-muhammad/
Al Hakam. (2021, January 29). Letters from Chachran: Khawaja Ghulam Farid’s Support of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.Retrieved from https://www.alhakam.org/letters-from-chachran-khawaja-ghulam-farids-support-of-hazrat-mirza-ghulam-ahmad/
Ahmadiyah Indonesia. Tafsir Ihdinā ṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm. Retrieved from https://ahmadiyah.id/khotbah/tafsir-ihdinash-shirotalmustaqiim
Ahmadiyah Indonesia. Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Dzilli dan Buruzi.Retrieved from https://ahmadiyah.id/mirza-ghulam-ahmad-sebagai-nabi-dzilli-dan-buruzi