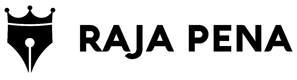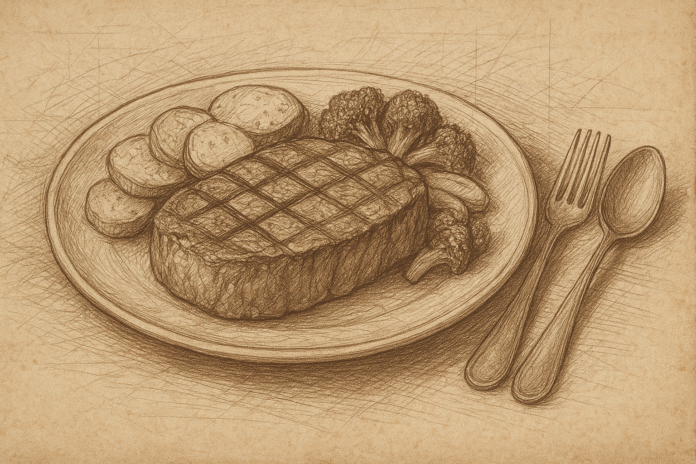Manusia selalu lapar. Bukan hanya pada makanan, tapi juga pada pengetahuan. Dari rasa ingin tahu itulah peradaban tumbuh. Ketika api pertama kali dikuasai, manusia bukan sekadar menemukan cara bertahan hidup. Ia menemukan rasa, mengubah bahan mentah menjadi santapan yang menggoda lidah. Namun rasa penasaran itu tidak berhenti di meja makan. Setelah puas dengan kelezatan, manusia mulai bertanya, apakah semua yang bisa dimakan memang layak untuk dimakan?
Dari semua jenis daging yang pernah dicoba manusia, ada satu yang selalu mengundang tanya besar, daging babi. Sejak ribuan tahun lalu, agama-agama besar terutama Islam melarangnya. Tapi larangan itu seakan tidak pernah benar-benar dihiraukan. Di banyak meja makan, daging itu tetap hadir, seperti suara yang dipelankan agar tidak terdengar hati nurani.
Memang, apa salahnya daging babi. Rasanya lezat, gurih, dan memuaskan hasrat manusia. Pertanyaan itu terus berulang, seolah lidah lebih berhak menentukan kebenaran daripada hati dan akal. Di sinilah letak rahasianya. Larangan ini tidak sekadar soal rasa, tapi soal makna. Rasa ternyata bukan hanya urusan lidah. Ia adalah jembatan antara tubuh dan jiwa, tempat manusia belajar membedakan nikmat dan nilai.
Ketika Rasa Masuk ke Jiwa
Apa yang kita makan tidak berhenti di perut. Ia membentuk tubuh, memengaruhi pikiran, dan perlahan membentuk tabiat. Seperti tanaman yang tumbuh dari kualitas tanah dan pupuknya, manusia pun tumbuh dari kualitas makanan yang ia pilih.
Karena itu, Allah Ta‘ala berfirman:
يٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ ٱلطَّيِّبٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صٰلِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعۡمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
“Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Ayat ini menegaskan hubungan langsung antara apa yang dimakan dan kemampuan berbuat baik. Perintah makan datang lebih dulu daripada perintah beramal, seolah mengingatkan bahwa amal saleh lahir dari sumber yang bersih. Di situlah tanggung jawab manusia, bukan hanya mencari yang halal, tetapi memastikan apa yang dimakannya menumbuhkan kebaikan di dalam diri.
Mengenal Hewan yang Tidak Mengenal Batas
Babi dikenal sebagai hewan yang memakan apa saja, termasuk kotorannya sendiri. Dalam biologi, perilaku ini disebut coprophagia. Dari kebiasaan inilah banyak parasit berpindah ke tubuhnya, seperti cacing Trichuris suis yang dapat menular ke manusia.
Lebih dari sekadar kebiasaan makan, tabiat babi terlihat dari cara ia hidup. Hewan ini senang berguling di lumpur, perilaku yang dalam biologi disebut wallowing. Secara ilmiah, kebiasaan itu membantu menurunkan suhu tubuh, melindungi kulit dari matahari, dan mengurangi parasit. Namun citra yang tertinggal bukan tentang fungsi, melainkan tentang lingkungan tempat ia merasa nyaman, tempat yang kotor dan tercemar. Dari situ, sifat jasmaninya terbaca jelas.
Dalam hal reproduksi, babi memiliki dorongan seksual yang tinggi dan tidak teratur. Mereka sering berganti pasangan tanpa pola tetap, bahkan perilaku sesama jenis juga kerap muncul. Dalam pandangan biologi, ini bagian dari naluri mempertahankan spesies. Namun dari sisi spiritual, perilaku yang tanpa kendali ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, ketidakseimbangan antara dorongan dan kesadaran.
Ilmu bisa menjelaskan bagaimana seekor hewan hidup, tetapi wahyu menjelaskan mengapa manusia tidak seharusnya menirunya.
Larangan yang Mengandung Didikan
Setiap larangan dari Allah selalu mengandung pelajaran. Apa yang masuk ke tubuh ikut membentuk jiwa, sebagaimana perilaku lahir mencerminkan isi batin. Hewan yang hidup dari sesuatu yang kotor akan menanggung akibatnya pada tubuh dan tabiatnya. Maka ketika dagingnya dikonsumsi, pengaruh itu ikut berpindah kepada manusia.
Karena itu, ketika manusia memakan daging hewan yang hidup dalam kekotoran, pengaruhnya tidak berhenti di tubuh. Ia merembes perlahan ke dalam jiwa. Dari sisi jasmani, penyakit bisa muncul dari dagingnya. Dari sisi ruhani, tumbuh kecenderungan pada hidup yang kacau, kendali diri yang lemah, dan hati yang sulit tenang. Larangan ini bukan semata demi kesehatan, tetapi demi menjaga kebersihan batin manusia.
Hz. Masih Mau’ud a.s. menjelaskan dalam Islami Ushul Ki Filasafi (Filsafat Ajaran Islam) bahwa bahkan nama “babi” dalam Al-Qur’an sudah menyiratkan sebab pengharamannya. Kata yang digunakan adalah خنزير (khinzīr), gabungan dari خَنَز (khanaz) dan أَرَ (ar) yang bermakna “aku melihatnya sebagai sesuatu yang rusak dan kotor.” Sejak awal, Allah Ta‘ala menamai makhluk ini dengan sebutan yang membawa makna keburukan, sebagai isyarat bahwa ia tidak layak menjadi makanan manusia. Maka jelas, larangan ini bukan hanya demi menjaga tubuh, tetapi juga demi memelihara kesucian jiwa.
Ruang Bernapas dalam Syariat
Agama tidak datang untuk membebani manusia. Larangan yang Allah tetapkan bukan belenggu, melainkan pagar agar manusia tidak tersesat. Hidup tak selalu berjalan di jalan lapang. Ada saat ketika pilihan yang tersisa hanya antara hidup dan mati. Keringanan ini bukan tanda kelemahan hukum, melainkan kelembutan Tuhan yang memahami batas daya manusia.
Di saat seperti itu, syariat membuka ruang keringanan. Al-Qur’an menegaskan:
فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
“Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Apa arti terpaksa dalam ayat ini. Menurut Imam Raghib, اضطرار(idzṭirār) ialah keadaan ketika seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya ia benci, atau ketika ia menghadapi bahaya bagi dirinya. Darurat bisa muncul dari luar, saat hidup terancam oleh ancaman nyata, atau dari dalam, ketika lapar berubah menjadi ancaman bagi kehidupan itu sendiri.
Pertama, seseorang tidak boleh menjadi بَاغٍ (bāghin), yaitu orang yang sengaja menentang aturan. Misalnya, seorang Muslim sedang bertamu di rumah temannya yang non-Muslim. Ketika dihidangkan babi, ia memakannya dengan ringan hati. Itu bukan darurat, tetapi penolakan terhadap perintah Tuhan.
Kedua, ia tidak boleh menjadi عَادٍ (‘ādin), yaitu orang yang melampaui batas. Artinya, jika benar-benar terpaksa memakan babi, ia hanya boleh memakannya sekadar untuk bertahan hidup, bukan untuk bersenang-senang atau makan hingga kenyang.
Bayangkan seseorang tersesat di hutan selama berhari-hari tanpa makanan. Tubuhnya lemah, nyawa hampir hilang. Dalam keadaan seperti itu, ia menemukan seekor babi. Pada saat itu, syariat membolehkan ia menyembelih dan memakannya, hanya untuk mempertahankan hidup.
Tetapi keringanan ini tidak berlaku bagi mereka yang sengaja menciptakan keadaan darurat. Jika seseorang sekadar menahan lapar sejak pagi lalu menjadikannya alasan untuk memakan babi, itu bukan idzṭirār yang dimaksud Al-Qur’an. Dalam Islam, darurat harus nyata, mendesak, dan tidak menyisakan pilihan lain. Rahmat selalu terbuka, tapi ia hanya menyentuh hati yang jujur terhadap dirinya sendiri.
Ketika Ampunan Menyertai Keringanan
Keringanan yang Allah berikan memang menenangkan. Tetapi keadaan darurat tidak otomatis menjadikan seseorang bertakwa. Tidak selalu demikian.
Dalam ayat tentang larangan memakan daging babi, Al-Qur’an menutupnya dengan firman:
إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
“Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Di sini muncul pertanyaan. Jika seseorang memakan babi karena terpaksa, mengapa sifat Tuhan yang disebut justru Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Bukankah itu terdengar seperti, “tidak apa-apa,” tetapi tetap harus memohon ampun?
Mungkin jawaban itu ada di dalam keadaan darurat itu sendiri. Situasi semacam itu bisa menjadi cermin atas sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, dosa atau kelalaian yang kini menampakkan akibatnya. Setiap perbuatan membawa jejak, dan kadang jejak itu baru terlihat ketika jalan sudah buntu.
Karena itu, bila seorang mukmin benar-benar terpaksa melakukannya, ia perlu menundukkan kepala dan bertanya dalam hati apa kesalahan yang mungkin telah menuntunnya sampai ke titik ini. Dari sanalah penyesalan yang jujur lahir. Tidak satu pun nabi, wali, atau manusia suci yang pernah sampai pada keadaan di mana ia harus memakan yang diharamkan.
Hidangan Penutup
Pembahasan ini panjang, seperti ajaran Tuhan yang tampak sederhana namun menyimpan banyak rahasia. Setiap ciptaan memiliki manfaatnya, tetapi tidak semua diciptakan untuk dimakan.
Perhatikanlah meja makan kita. Apakah yang tersaji di atasnya menumbuhkan keimanan, atau justru mengundang kelalaian. Setiap suapan adalah pilihan tentang siapa diri kita, dan setiap rasa akan bersaksi di hadapan Tuhan tentang asalnya. Sains mungkin berkata daging itu aman, tapi Tuhan menilai bukan dari kandungan gizinya.
Semoga setiap rezeki yang datang tidak hanya mengenyangkan tubuh, tapi juga menumbuhkan jiwa untuk mendekat kepada-Nya. Āmīn.
Oleh : Ilham Sayyid Ahmad
Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Terjemahan
- Al-Qur’an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat Bahasa Indonesia. Neratja Press, Jakarta. Edisi 2023.
- Surah Al-Mu’minūn [23]: 52. Jilid 2.
- Surah Al-Baqarah [2]: 174. Jilid 1.
Sumber Tafsir
- Mirza Ghulam Ahmad. Islami Ushul Ki Falasafi (The Philosophy of the Teachings of Islam). Dalam Ruhani Khazain, Jilid 10, hal. 338. Edisi Urdu. Percetakan Ziaul Islam, Qadian, 1905.
- Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Tafsir Kabir (Edisi Baru), Jilid 3, hal. 122–123.
Referensi Sains dan Umum
- “Coprophagia.” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Coprophagia
- “Wallowing.” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Wallowing
- “Pig.” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pig
- Ar-Rāghib al-Ashfahānī, Abul Qāsim al-Husain bin Muhammad bin al-Fadhl. Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān (المفردات في غريب القرآن). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.