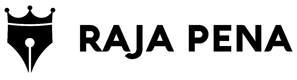Pendahuluan
Dalam diskursus publik modern, sains dan agama kerap digambarkan sebagai dua kubu yang berada pada kutub berseberangan. Ketegangan terjadi akibat kedua belah pihak sering mengasumsikan bahwa sains dan agama berbicara dalam ranah yang sama, menjawab jenis pertanyaan yang sama, dan memiliki otoritas epistemik yang identik. Padahal banyak ketegangan tidak lahir dari isi sains atau ajaran agama, melainkan dari kekeliruan menempatkan batas wilayah pengetahuannya. Untuk memahami sumber kekeliruan tersebut, perlu dipahami kedudukan epistemik, meninjau apa yang dimaksud dengan fenomena dan noumena.
Mengenai Fenomena dan Noumena
Istilah fenomena dan noumena pertama kali dipopulerkan oleh Immanuel Kant melalui karyanya Critique of Pure Reason. Kant memperkenalkan kedua istilah ini untuk menjawab pertanyaan “apa sebenarnya yang manusia ketahui tentang dunia?“
Kant menyebut fenomena sebagai segala sesuatu sebagaimana tampak kepada manusia (apa yang dapat diamati, diukur, dan ditelusuri) melalui pengalaman empiris. Fenomena hanya merupakan sisi realitas yang terjangkau oleh persepsi.
Sebaliknya, noumena merujuk pada realitas sebagaimana adanya, terlepas dari bagaimana manusia melihatnya. Sehingga tidak dapat diindra maupun dijelaskan sepenuhnya melalui pengamatan. Konsep ini memang bersifat abstrak, karena Kant justru menegaskan bahwa manusia tidak memiliki akses langsung terhadap noumena.
Contoh sederhana dapat diambil dari hujan. Rintik air yang jatuh, suara di atap rumah, dan turunnya suhu udara adalah fenomena—hal-hal yang dapat diamati dan dijelaskan secara ilmiah. Namun “hujan itu sendiri” sebagai realitas murni, sebelum kita persepsikan sebagai menenangkan, atau membawa suasana tertentu, berada di sisi noumena. Hujan sebagai fenomena adalah apa yang tampak; hujan sebagai noumena adalah apa adanya sebelum diproses oleh pengalaman dan asosiasi kita.
Pembedaan singkat ini menunjukkan bahwa manusia selalu berurusan dengan fenomena dalam memahami dunia, sementara noumena tetap berada di luar jangkauan langsung.
Ketika Sains Masuk Ranah Noumena, dan Agama Masuk Ranah Fenomena
Pembedaan antara fenomena dan noumena membantu kita melihat bahwa banyak ketegangan antara sains dan agama muncul bukan karena keduanya benar-benar bertentangan, tetapi karena batas wilayah pengetahuannya sering tertukar.
Ketika Sains Diminta Menjawab Pertanyaan Noumena
Masalah muncul ketika sains melampaui batas metodologinya dan menganggap dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Pada titik itu sains berubah menjadi saintisme. Batas ini terlihat jelas ketika kita meninjau persoalan-persoalan filosofis yang menunjukkan sejauh mana kemampuan sains dapat bekerja, dan sejauh mana ia harus berhenti.[1] Keterbatasan ini telah lama dijelaskan para pemikir besar melalui argumen yang menunjukkan bahwa sains hanya bekerja di wilayah fenomena dan tidak memiliki akses langsung ke noumena.
René Descartes memulai dengan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana manusia dapat benar-benar yakin terhadap pengetahuannya. Ia menyadari bahwa untuk membangun pengetahuan yang kokoh, seseorang memerlukan dasar yang tidak dapat diragukan. Namun ketika seseorang mencoba membuktikan bahwa pengamatan dapat dipercaya, pembuktian itu justru memakai pengamatan itu sendiri. Hal yang sama terjadi ketika seseorang mencoba membuktikan logika; pembuktian tetap menggunakan logika yang sama. Situasi ini menyerupai usaha memastikan apakah sebuah kamera bekerja dengan baik, tetapi satu-satunya alat yang kita miliki untuk mengeceknya adalah gambar dari kamera tersebut. Kita tidak pernah keluar dari sistem itu untuk melihatnya dari luar. Karena sains bergantung sepenuhnya pada pengamatan dan penalaran manusia, sains tidak punya cara untuk melampaui keduanya. Menurut Descartes, sains sejak awal hanya bekerja dalam dunia fenomena, bukan noumena, karena alat untuk keluar dari sistem pengetahuan manusia tidak pernah tersedia.[2]
Pandangan dasar mengenai keterbatasan ini kemudian diperkuat oleh David Hume. Hume menyoroti bahwa banyak keyakinan ilmiah bertumpu pada kebiasaan pikiran, bukan bukti logis. Kita percaya api akan membakar kertas pada hari esok karena selama ini selalu begitu. Namun keyakinan bahwa masa depan harus mengikuti pola masa lalu tidak pernah memiliki jaminan empiris. Hume menunjukkan bahwa sains membaca kebiasaan fenomena, bukan hakikat di balik fenomena. Karena itu sains hanya mengetahui bahwa sesuatu terjadi, bukan mengapa realitas harus berjalan demikian. Dengan logika ini, sains tidak pernah menyentuh noumena karena ia tidak memiliki alat untuk menembus dasar terdalam keberadaan.[3]
Immanuel Kant kemudian memberikan dasar yang paling kuat dalam membedakan fenomena dan noumena. Kant menegaskan bahwa batas sains adalah batas pikiran manusia itu sendiri, sehingga metode ilmiah memang tidak pernah dirancang untuk menembus noumena.[4]
Gagasan Kant mengenai struktur pengalaman ini kemudian diperluas oleh W. V. O. Quine melalui persoalan hubungan antara data dan teori. Quine menunjukkan bahwa satu set data empiris dapat dijelaskan oleh beberapa teori yang berbeda. Para ilmuwan tidak hanya mengikuti data, tetapi juga mengikuti pola pikir, kebiasaan intelektual, rumusan dan kerangka konseptual yang dominan pada zamannya. Sebagai contoh, sebelum model heliosentris diterima secara luas, model geosentris pun dapat disesuaikan dengan pengamatan tertentu. Dengan demikian, teori ilmiah hanyalah model, bukan cermin realitas terdalam. Hal ini berarti sains tetap berada pada wilayah fenomena dan tidak pernah memasuki noumena.[5]
Ludwig Wittgenstein kemudian menyoroti batas lain yang tidak dapat dilewati oleh sains, yaitu bahasa. Menurut Wittgenstein, apa yang dapat dipikirkan dan dibicarakan manusia selalu dibatasi oleh bahasa yang tersedia. Sains seluruhnya bekerja melalui bahasa dan matematika sehingga pernyataannya tidak pernah keluar dari batas simbol-simbol tersebut. Jika bahasa tidak memiliki konsep untuk menggambarkan suatu aspek realitas, aspek tersebut tidak dapat masuk ke pembahasan ilmiah. Dalam kerangka ini, noumena berada di luar wilayah sains, bukan karena sains kurang canggih, tetapi karena noumena berada di luar batas bahasa manusia.[6]
Seluruh penjelasan para filsuf tersebut mengarah pada satu kesimpulan yang konsisten. Sains bekerja dalam ranah fenomena dan tidak memiliki akses menuju noumena. Batas instrumen manusia, kebiasaan pikiran, struktur kesadaran, pilihan teoretis, dan keterbatasan bahasa semuanya menunjuk pada hal yang sama. Dengan menyadari batas ini, sains tetap berada pada wilayah empiris tanpa dipaksa menjawab pertanyaan yang berada di luar jangkauan metodenya.
Ketika Agama Dipaksa Menjelaskan Fenomena Secara Teknis
Agama berbicara tentang makna, nilai, dan panduan hidup. Bahasa agama umumnya mengajak manusia merenungkan tujuan keberadaan, memperbaiki diri, dan memahami hubungan dengan sesama. Karena sifatnya reflektif, agama beroperasi pada wilayah yang berbeda dari sains, sehingga lebih dekat dengan ranah noumena. Kesalahpahaman muncul ketika agama dipaksa menjelaskan fenomena alam secara teknis, padahal bahasa kitab suci tidak dirancang untuk mengurai mekanisme material.[7]
Kekeliruan paling umum terjadi ketika seseorang menyamakan pemahaman manusia dengan firman Tuhan itu sendiri. Wahyu memang berasal dari Tuhan, tetapi apa yang sampai kepada kita sehari-hari (seperti Al-Quran yang dicetak di atas kertas, terjemahan ke berbagai bahasa, tafsir ulama, serta pemahaman yang lahir dari pengalaman dan budaya) semuanya adalah produk manusia. Semua itu adalah fenomena: “peta” manusia yang berusaha memahami sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya.[8] Menyebut interpretasi manusia sebagai kebenaran mutlak artinya mengaburkan perbedaan antara peta dan wilayah, antara representasi dan realitas.
Sejarah penafsiran tradisi Islam memperjelas hal ini. Al-Qur’an dibaca dan dijelaskan oleh sahabat Nabi, lalu oleh generasi berikutnya. Karya-karya tafsir itu sangat berharga, tetapi tetap merupakan hasil usaha manusia. Penjelasan mereka dipengaruhi oleh ilmu dan kosmologi yang tersedia pada masa itu, oleh budaya Arab klasik, serta oleh konteks sejarah dan sosial politik dari zaman tersebut.[9] Tafsir adalah jembatan yang dibangun manusia untuk mendekati wahyu; tafsir bukan wahyu itu sendiri. Karena itu tafsir adalah fenomena, sedangkan wahyu yang menjadi sumber tetap merupakan noumena.[10]
Contoh yang sering menimbulkan kebingungan muncul dalam isu kosmologi. Banyak mufasir klasik menafsirkan ayat-ayat yang mendeskripsikan alam semesta sesuai pengetahuan astronomi mereka. Itu bukan kesalahan, melainkan bentuk ijtihad intelektual di masa itu. Permasalahan muncul ketika pembaca modern memandang tafsir lama sebagai deskripsi fisika yang final, seakan-akan pengetahuan manusia tidak berkembang.[11] Pada titik itu, agama tampak bertentangan dengan sains, bukan karena wahyu konflik dengan sains, tetapi karena tafsir manusia dijadikan rujukan pasti untuk memahami alam.
Dari sinilah dogmatisme lahir. Ketika seseorang tidak mampu membedakan fenomena dan noumena, interpretasi manusia dianggap sebagai kebenaran absolut. Budaya, latar belakang, dan konteks sosial diperlakukan seolah universal. Bahasa agama yang seharusnya membuka ruang refleksi berubah menjadi tembok yang membatasi kemungkinan pemahaman baru.[12]
Pembedaan antara fenomena dan noumena memberi kita jalan keluar dari kebuntuan ini. Agama tidak dirancang untuk menjelaskan bagaimana alam bekerja secara ilmiah, agama hadir untuk membantu manusia memahami mengapa hidup memiliki makna. Jika wahyu diumpamakan sebagai matahari, maka tafsir dan pemahaman manusia adalah sinar yang sampai kepada kita. Sinar itu memberi arah dan pengharapan, tetapi tidak sama dengan sumbernya. Menyadari jarak ini menumbuhkan kerendahan hati, bahwa pemahaman manusia hanyalah peta, sementara wilayah kebenaran ilahi jauh lebih luas daripada apa yang bisa kita tangkap.[13]
Penutup
Memahami perbedaan antara fenomena dan noumena membantu menempatkan sains, agama, dan pemahaman manusia pada ruangnya masing-masing. Sains bekerja pada wilayah yang teramati, agama membahas makna dan tujuan, sedangkan manusia bergerak di antara keduanya dengan kemampuan yang terbatas.
Bagi umat beragama, kesadaran ini mengingatkan bahwa penafsiran agama adalah hasil kerja manusia dalam memahami pesan yang lebih besar. Hal ini mencegah kekakuan dan membuka ruang untuk keragaman pandangan.
Bagi ilmuwan, pemahaman tentang batas metodologi menjaga sains tetap pada wilayahnya. Sains menjelaskan mekanisme dunia dengan baik, namun tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup atau nilai moral.
Bagi setiap orang, menyadari keterbatasan persepsi membantu kita melihat bahwa sudut pandang kita tidak pernah mutlak. Pengalaman hidup dan budaya membentuk pemahaman kita, sehingga kita dapat lebih terbuka dan tidak menganggap pandangan pribadi sebagai satu-satunya kebenaran.
Menerima batas pengetahuan justru memberi landasan untuk memahami dunia. Dengan cara ini, sains dan agama dapat berdampingan tanpa saling meniadakan.
Oleh: Danish Ahmad
Catatan Kaki:
[1] Ian G. Barbour, Religion and Science: Historical and Contemporary Issues (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1997).
[2] René Descartes, Meditations on First Philosophy, ed. John Cottingham (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
[3] David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, ed. Tom L. Beauchamp (Oxford: Oxford University Press, 2000).
[4] Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
[4] W. V. O. Quine, From a Logical Point of View 2nd edition (Cambridge MA Harvard University Press, 1953).
[6] Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (London: Routledge, 2001).
[7] Ian G. Barbour, Religion and Science: Historical and Contemporary Issues (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1997).
[2] Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
[8] Walid A. Saleh, The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Qur’an Commentary of al-Tha’labi (d. 427/1035) (Leiden: Brill, 2004).
[10] Seyyed Hossein Nasr et al., eds., The Study Quran: A New Translation and Commentary (New York: HarperOne, 2015).
[11] Nidhal Guessoum, Islam and Science: Contemporary Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2023).
[11] Ebrahim Moosa, What Is a Madrasa? (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2015).
[13] Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
Image:
ChatGPT Image 20 Des 2025