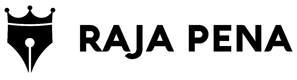Redaksi ini terilhami oleh kumpulan cerpen A.A. Navis khususnya oleh judul satu cerpen Navis, Robohnya Surau Kami, yang kemudian dijadikan judul buku tersebut.
Sekolah dalam Lintasan Sejarah
Adalah Ivan Illich sosok visioner yang bertekad merobohkan sistem persekolahan dengan tesisnya Deschooling Society (Masyarakat Nirsekolah).[1] Betapa tidak dalam buku yang hanya berhalaman 116, Illich membuka buku tersebut dengan esainya yang galak berjudul Why Must We Disestablish School? Sebuah masyarakat nirsekolah. Ini jelas sebuah pemberontakan.
Jadi pandemi Covid-19 yang sempat merumahkan 60% peserta didik di seluruh dunia sebagaimana dilansir laman resmi Unesco[2] ternyata bukanlah satu-satunya penentang atas supremasi sang penguasa pendidikan formal yang bernama sekolah. Illich sudah mencoba melakukannya tahun 1970. Dan bila Covid-19 bersifat interuptif—atau kemudian lebih populer dengan istilah disruptif—memotong batang pohon besar sekolah, maka Illich berusaha mencerabut dari akarnya.
Menarik untuk mencermati apa yang disampaikan oleh Iwan Pranoto. Dia berpendapat bahwa bagaimanapun tidaklah mudah untuk menggantikan model pendidikan formal yang sudah berjalan dua setengah milenia ini.
Ternyata lebih lampau dari itu, lembaga pendidikan formal tercatat sudah ada sejak 3000 SM di Sumeria, Mesopotamia sebagaimana kita baca dalam artikel kecil oleh Kassioun[3]:
”فقد رافق استخدام الكتابة، ظهور مدارس لتعليمها في بلاد الرّافدين نحو /3000/ ق. م، وهي المدارس الأولى في العالم، وكان هناك بيوت خاصة اسْتُخدِمَت للتعليم، إضافة إلى المعابد، والقصور الملكية. وتقوم على تدريس الكهنة الّذين سيشغلون الوظائف داخل المعبد أو في خدمة الدّولة….
وكانت العملية التعليمية تبدأ وتنتهي بصلاة أو دعاء اللوح والقلم: «أيّها الرّقم كن شفيعاً لي، تكلم من أجلي أمام الإله نابو..» أو «أيها الإله نابو، بصرني بإدراك الأمور» “
Dari artikel di atas—yang sayangnya tidak menyertakan sumber tulisan tersebut—kita mendapatkan gambaran sistem persekolahan yang persis seperti masa sekarang, ada penjenjangan kelas dengan kurikulumnya. Bahkan, pembelajaran di kelas tersebut diawali dan diakhiri dengan doa. Gambaran ini jauh lebih tua dibandingkan dengan tradisi kelas yang dipimpin seorang sophist di Yunani abad ke-5 SM.
Sekolah: Antara Glorifikasi dan Degradasi
Sekolah secara sejarah mengukuhkan diri sebagai lembaga yang memiliki kuasa besar atas legitimasi kepriyayian seseorang, kelompok bahkan bangsa. Sekolah sebagai lembaga nilai dari awal selalu memiliki kedekatan dengan sang pengampu nilai baik penguasa maupun pemimpin agama. Hingga kemudian Horace Mann (1796-1859) yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Modern meletakkan enam prinsip persekolahannya yang populer: (1) negara tidak boleh abai dan merasa bebas dari kewajiban pendidikan; (2) dibiayai, diatur dan diampu atas kepentingan masyarakat; (3) diikutsertai oleh semua anak tanpa melihat agama, latar belakang sosial dan kesukuan; (4) meski menekankan moral, tapi ia harus bebas dari pengaruh sektarianisme agama; (5) didasari semangat, metoda dan disiplin masyarakat bebas yang bersih dari segala unsur kekerasan di kelas; dan (6) dilaksanakan oleh guru-guru profesional yang terlatih.
Wajah persekolahan secara umum terinspirasi oleh enam prinsip sekolah modernnya Mann. Lalu sekolah pun semakin mentereng pamornya. Ia berdiri kokoh dengan jargon-jargon bombastik hingga pada puncaknya sekolah berubah menjadi sebatas menara gading. Glamor di permukaan namun tidak lagi berpamor. “Pelembagaan nilai ini secara tak terelakkan mengakibatkan polusi fisik (merebaknya gedung sekolah bak cendawan di musim hujan dengan mengabaikan lingkungan sekitar), polarisasi sosial (priyayi dan abangan) dan impotensi psikologis (glorifikasi keilmuan yang menumpulkan rasa dan tepa selira): tiga dimensi dalam sebuah proses kemerosotan nilai-nilai asasi secara global dan kesengsaraan baru bercorak modern,” demikian ungkap ketus Ivan Illich.
Kekeroposan inilah yang membuat sistem persekolahan tidak lantas sebangun dengan pendidikan. Peter Gray dalam A Brief History of Education-nya turut mengkritisi kondisi ini dengan kata-katanya:
“With the rise of schooling, people began to think of learning as children’s work. The same power-assertive methods that had been used to make children work in fields and factories were quite naturally transferred to the classroom.”
Sekolah kehilangan sentuhan pendidikannya. Ia secara mengenaskan berubah. Ketika orang berpikir bahwa belajar adalah pekerjaan anak. Maka semangat yang sama–yang telah digunakan untuk mempekerjakan anak-anak di ladang dan pabrik secara alami—dipindahkan ke ruang kelas. Sekolah berubah menjadi semacam kelas bagi trainee secara kultural. Sekolah tidak lagi menjadi harapan untuk liberasi pemikiran, kebun subur untuk gagasan atau pengembangan kompetensi diri yang murni. Sebentuk perlawanan sempat dilakukan oleh sekolah-sekolah tapi ironisnya kemudian berujung sama tirannya. Itulah impotensi psikoligis sebagaimana disitir oleh Illich.
Banyak pegiat pendidikan yang berupaya merevitalisasi sistem persekolahan. Bahkan ada yang secara esktrem mendirikan sekolah alternatif dengan memfokuskan pengembangan potensi peserta didiknya. Harus diakui bahwa sistem pendidikan formal berupa sekolah masih sangat diperlukan–namun sekaligus perlu terus dikritisi dan diperbaiki.
Kondisi inilah yang membuka mata seorang Muhammad Yunus. Yunus menggap kampus tempat ia mengajar tidak lagi peka terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan. “Apa hebatnya teori ekonomi yang saya ajarkan itu manakala ada orang-orang yang sekarat di trotoar di seberang tempat saya mengajar sedang bergelut dengan rasa sakit yang mencekik?” ujarnya meradang. Yunus kemudian mendapatkan anugerah Nobel Perdamaian atas prakarsanya membumikan ilmu dengan konsep sebagaimana tergambar dalam bukunya yang berjudul Bank Kaum Miskin.
Sekolah Ramah Kemanusiaan
Pada awal perkembangan Islam periode Medinah, demi melihat posisi strategis pendidikan bagi kaum muslimin, Rasullullah membuat ruang khusus di masjid Nabawi yang disebut suffah. Para sahabat yang papa atau musafir sehari-hari tinggal di sana. Baik berupa halaqah (lingkaran kecil sambil lesehan) atau obrolan satu atau beberapa orang, proses transfer keilmuan berjalan. Tentu saja kegiatan pendidikan dan keilmuan berpusat kepada Rasulullah saw. Sejarah persekolahan di dunia Islam yang pertama kali berdiri di dunia Islam sebagai lembaga pendidikan yang bentuk dan sistemnya mendekati seperti sekarang adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk (1018-1092), seorang penguasa bani Seljuk pada abad ke-11 M.
Namun uniknya perguruan tinggi pertama di dunia Islam—bahkan sejauh ini tercatat sebagai perguruan tinggi pertama di dunia—malah berdiri jauh sebelum itu yaitu Al-Qarawiyyin yang didirikan atas prakarsa Fatimah al-Fihri pada tahun 859 di Fes, Maroko. Di Indonesia sendiri sistem persekolahan yang tertua adalah pecantrikan (dalam tradisi Hindu-Buddha) yang lalu setelah kedatangan Islam kemudian diadaptasi menjadi pesantrian atau pesantren.
Suasana pembelajaran dalam sistem halaqah, pecantrikan atau pesantren ternyata lebih ramah kehidupan. Bila sekarang kita sering mendengar frasa sekolah ramah anak nampaknya masih tidak terlalu inovatif dibanding dengan sistem persekolahan sebelumnya. Ironisnya boleh jadi konsep sekolah ramah anak pun lahir dari kritik Gray. Banyaknya jumlah mata pelajaran yang wajib diikuti peserta didik, durasi pembelajaran klasikal di sekolah, penekanan persaingan yang mengikis kerjasama dan sistem penilaian yangsebatas permukaan menjadikan sistem persekolahan terlalu linear dan kurang kejutan. Nampaknya ini sudah disadari dan sedang diperbaiki para pemangku kepentingan.
Keriangan bersekolah, pembumian konsep yang melangit, penerapan teori dalam keseharian dan pembelajaran yang senafas dengan realitas yang dihadapi—namun sekaligus adaptif terhadap perkembangan—adalah cita-cita besar sekolah. Sekolah punya kewajiban untuk menumbuhkan potensi belajar mandiri di kalangan peserta didiknya. Iwan Pranoto menyebut potensi ini dengan istilah swaajar sementara Zimmermann menyebutnya sebagai self-regulated learning. Potensi inilah yang wajib ada dalam setiap peserta didik dan sekolah wajib menumbuhkannya. Bila ini ada maka keriangan bersekolah akan tumbuh. Seriang anak kecil yang belajar dari alam.
Menyangga Bersama Pohon Sekolah
Namun apa dikata. Belum adanya kualitas atau mental swaajar ini yang mengakibatkan sistem persekolahan nyaris roboh saat pandemi Covid-19 memaksa pembelajaran secara daring. Keluhan di sana-sini bermunculan baik peserta didik maupun orangtua. Bila dengan tatap muka saja sistem persekolahan sudah limbung mengimbangi parahara tantangan global, maka pembelajaran daring bisa saja merobohkannya. Kita mesti berangkat dari rumah sebagai sistem pendidikan terkecil dan pertama. Penyelenggara dan para pemangku kepentingan pendidikan formal pun—dalam hal ini persekolahan—harus mengevaluasi diri secara kritis.
Pendidikan bukanlah hal yang sederhana karena memang ia dimaksudkan untuk berhadapan dengan kehidupan yang tidak sederhana. Pendidikan itu rumit karena manusia sebagai subjeknya sendiri memang unik. Sistem persekolahan yang didapuk untuk mengemban tugas pendidikan secara formal tidak boleh keluar dari khithtah ini. Bukankah Socrates pernah menasihati kita bahwa education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel?
Ya, pendidikan adalah menyalakan api, dan bukannya mengisi bejana.
Oleh : Dodi Kurniawan
Sumber :
[1] Illich, Ivan (2018). Deschooling Society. Camas Books.
[2] https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
[3] https://kassioun.org/more-categories/art-and-culture/item/38328-11869
Sumber Gambar : studyinternasional.com