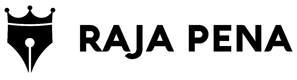Ketika melintasi toko kelontong itu, sekejap aroma dupa semerbak merasuki rongga hidung. Saya berhenti sejenak. Diratapinya morfologi toko yang tak biasa dari toko-toko modern pada zaman ini. Atapnya yang bergaya Ngang Shan memiliki lekukan persis menyerupai pelana kuda. Toko itu identik dengan warna merah serta dibumbui corak-corak berwarna emas. Banyak elemen seperti naga dan aksara-aksara kanji yang terpatri pada dinding atau hiasan-hiasan gantung, juga ada lampion merah dari berbagai ukuran, tentu untuk dijual. Karena melihat tingkah saya, seorang wanita paruh baya berkulit kuning langsat dan kelopak matanya yang sipit layu menghampiri dan menyambut saya untuk melihat-lihat lebih banyak barang apa yang ada di dalam toko. Tanpa disadari, ketika melihat suasana jalan di sekitar toko, saya seperti berada di kawasan Chinatown yang sangat estetik. Usut punya usut, sepanjang jalan tersebut sarat akan sejarah dimana etnis Tionghoa telah bermukim sejak berabad-abad yang lalu. Wajar jika banyak ditemukan bangunan-bangunan bergaya Tionghoa yang berusia ratusan tahun berjejer sepanjang jalan.
Setiap perayaan tahun baru Imlek, jalan tersebut ramai dikunjungi masyarakat dan menjadi daya tarik wisata yang cukup memikat. Pertunjukan Barongsai menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh warga yang sudah berkerumun dari awal waktu. Biasanya semarak perayaan Imlek berlangsung hingga Cap Go Meh pada tanggal 15 awal tahun baru penanggalan Tionghoa.
Namun, dibalik panggung acara Barongsai dan kemeriahan Imlek di tanah air tersimpan kisah pasang surut eksistensi saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa. Tak jarang mereka mengalami persekusi serta stereotype yang bahkan hingga kini masih dicap oleh sebagian orang. Rupanya isu-isu rasial yang dialamatkan oleh kelompok tertentu terhadap etnis Tionghoa sudah berlangsung ratusan tahun sebelum negara ini merdeka.
Namun sejatinya, bila kita mengulur linimasa sejarah perjalanan Indonesia, orang-orang Tionghoa sudah menjajakkan kakinya di Nusantara sejak zaman Dinasti Han dengan berbagai tujuan dan diterima baik oleh penduduk lokal. Bahkan ketika kerajaan Majapahit berjaya pun banyak komoditi mahal dari Tiongkok yang diperjualbelikan, seperti porselen dan sebagainya. Riuh ramai suasana perdagangan kala itu terjadi dengan harmonis antara warga asli dengan pendatang seperti orang-orang Tionghoa.
Lantas bagaimana tren isu rasial ini bisa semerbak aromanya hingga detik ini?
Ketika VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie/kongsi dagang Belanda di Hindia Timur) bercokol di Nusantara pada abad ke-18, Belanda banyak membuat peraturan yang ‘mengotak-kotakan’ masyarakat berdasarkan etnis, seperti etnis Eropa, Cina, Arab, Melayu, India, ataupun pribumi. Karena ‘rasis’-nya ini, Belanda juga membuat sejumlah aturan perjalanan bagi orang non-Eropa terutama Cina, mereka harus menyerahkan passenstelsel atau semacam passport ketika melakukan perjalanan meskipun dekat. Hal ini lambat laun berdampak pada permasalahan ekonomi.
Dalam sejarah, pernah meletus peristiwa ‘Geger Pacinan’ atau Perang Sepanjang (1740-1743). Geger Pacinan merupakan pogrom terhadap etnis Tionghoa di Batavia. Karena masalah terkait industri gula dimana orang Tionghoa lebih unggul dalam bisnis tebu di saat harga gula dunia sedang lesu, VOC mengalami paranoia dan menaruh prasangka sehingga orang-orang Tionghoa yang mencurigakan dideportasi. Namun dalam perjalannya, mereka dibuang ke laut hidup-hidup. Keluarga yang tinggal di Batavia dan sekitarnya mengetahui hal tersebut marah dan memberontak. Mereka menggencarkan serangan kepada Belanda. Dan di bawah otoritas Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier, ada instruksi untuk membunuh orang-orang Tionghoa, ada yang melalui proses peradilan di depan Stadhuis (sekarang Museum Sejarah Jakarta), ada pula yang dibantai langsung secara kejam, lantas mayatnya dibuang percuma ke kali Angke.
Peristiwa ini berlangsung di kota-kota lain di Jawa. Masyarakat Tionghoa dipimpin oleh Kapitan Sepanjang di Batavia, sementara Tan Sin Ko di Jawa dan orang pribumi dipimpin oleh Sunan Amangkurat V di Jawa. Antara 1860 hingga 1905, populasi orang Tionghoa di Indonesia meningkat dari 221.000 orang menjadi 563.000 orang, peningkatan ini terjadi masif di pulau Sumatera karena ribuan kuli dipekerjakan di tembakau dan perkebunan karet.
Banyaknya populasi orang Tionghoa tak menyurutkan kebencian terhadap mereka bahkan ketika Belanda sudah angkat kaki dari negeri merdeka ini sekalipun. Karena guncangan krisis ideologi dan politik identitas, isu rasial pun diangkat, lalu dijual ketika memasuki masa Orde Baru (1965) dan pergantian presiden. Dan laku. Buktinya, semua organisasi dan sekolah Tionghoa ditutup, menyusul tuduhan kudeta yang ditengarai oleh sebuah partai ideologi di Indonesia, belum lagi banyak kebijakan yang melarang aktivitas beraroma Tionghoa, juga melarang penggunaan nama Tionghoa bagi penduduk. Pecahlah kerusuhan-kerusuhan anti-Tionghoa, penjarahan, pembakaran toko, bahkan ada yang dibunuh segala.
Saat peristiwa kerusuhan 1998, etnis Tionghoa kembali menjadi korban kekerasan, penjarahan dan diskriminasi hebat. Kesenjangan ekonomi dan kebencian berdasarkan prasangka rasial terhadap etnis Tionghoa menimbulkan gejala Xenofobia. Dalam persitiwa tersebut banyak perempuan-perempuan Tionghoa yang diperkosa, dan tokonya dibakar sampai-sampai muncul budaya ‘pasang tralis’ pada toko-toko karena (mungkin) dampak traumatis dari penjarahan itu.
Berakhirnya Orde Baru dan menjajaknya era reformasi, warga etnis Tionghoa sedikit menghela napas lega karena pemerintah melonggarkan kebijakan yang sempat mencekik warga Tionghoa di Indonesia, salah satunya dapat merayakan tahun baru Imlek.
Sebuah peristiwa politik tahun 2017 juga pernah menimbulkan polarisasi yang cukup kental di masyarakat. Dengan menjual isu rasial antara “pribumi” dan “asing”, masyarakat digiring dan digoreng opininya. Isu rasial dibumbui isu agama menjadi sangat laku dan berhasil mengotak-kotakan masyarakat. Persis seperti zaman penjajahan dulu.
Baru-baru ini, pandemi Covid-19 juga tak luput dari penuduhan negara Tiongkok tempat virus corona muncul sebagai sumber konspirasi atas balabencana yang terjadi di dunia ini. Banyak yang percaya bahwa Covid-19 adalah “buatan Cina” sehingga mengabaikan protokol kesehatan karena menganggap isu virus corona hanyalah produk konspirasi. Lagi-lagi, “Cina” disudutkan.
Filsuf dan sosiolog Perancis Maurice Halbwach, mengungkapkan bahwa ingatan kolektif masyarakat dibentuk berdasar kesepakatan sosial. Konstruksi stigma terhadap orang Tionghoa ini telah melalui proses panjang sejarah dan melekat di dalam memori kolektif masyarakat. Dan zaman sekarang, menyebut “Orang Cina” terdengar lebih nista ketimbang “Orang Tionghoa”.
Stereotype itu dapat diubah dengan menata ulang konstruksi “orang asing” agar menghindari konflik. Mempelajari sejarah juga harus dilakukan dengan apik untuk mengetahui keterlibatan warga Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga masyarakat dapat menghargai eksistensi orang Tionghoa di Indonesia.
Dalam bukunya yang berjudul ‘Jalan Raya Pos, Jalan Daendels’, Pramoedya Ananta Toer mengungkapkan, “Orang-orang Tionghoa inilah yang kemudian dengan jiwanya yang lebih mandiri dan merdeka serta kerajinannya yang luarbiasa berhasil meninggalkan statusnya sebagai pekerja paksa menjadi pengusaha dan pedagang, menguasai sektor ekonomi masyarakat Batavia.” Mungkin atas dasar hal tersebut, pihak oposisi menaruh syak-wasangka tak berkesudahan kepada etnis Tionghoa sejak zaman kolonial hingga milenial sekarang sampai-sampai saudara-saudara kita beretnis Tionghoa dilekatkan dengan berbagai stigma negatif.
Diskriminasi terhadap kaum Tionghoa menjadi coretan hitam bangsa Indonesia yang akan tetap terus dikenang sepanjang sejarah. Namun sudah saatnya kita menghapus stigma, stereotype dan asumsi negatif itu. Jika kita telaah kembali riwayat Rasulullah SAW ketika menyikapi isu rasisme, Beliau bersabda bahwa tidak ada orang (kulit) hitam yang lebih superior, tidak ada orang (kulit) putih yang lebih superior, tidak ada orang Arab yang lebih superior dari non-Arab, dan sebaliknya. Artinya, bahwa apapun ras, suku, dan etnisnya, tidak ada yang lebih unggul dan berhak mengungguli. Semua harus egaliter.
Al Quran-Karim juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mengutuk dan menindas orang tak bersalah. Sebaliknya, kita harus menyeruakan emansipasi bagi yang tertindas. Jelas, bahwa firman Allah Taala menetapkan bahwa setiap orang terlahir sederajat. Khalifah Islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad juga menugaskan kepada para Ahmadi untuk mengutuk aksi rasisme dan berupaya menempuh peradilan dan kesetaraan, contohnya dalam kasus rasisme Black Live Matters atas kematian George Floyd di Amerika Serikat.
Dijelaskan pula dalam QS Al Hujurat ayat 14 bahwa Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita sekalian dapat saling mengenal satu sama lain. Betapa sedihnya ketika banyak dari kita yang melanggengkan isu rasial ini dalam kehidupan kita demi kepentingan pribadi/golongan semata, sementara keragaman ras dan suku telah diniscayakan oleh firman Allah Taala sendiri.
Karena itu, saatnya kita membangun solidaritas dan kebersamaan. Buang jauh-jauh pemikiran rasis yang merupakan warisan dari masa lalu. Sudah saatnya kita menghidupkan cahaya kemanusiaan yang redup dengan amal kebaikan yang saat ini diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi Covid-19.
Alangkah senangnya saya setelah berjalan keluar dari toko itu sambil menjinjing kantong belanjaan berisi kue keranjang, pernak-pernik khas Imlek dan dupa untuk pengharum ruangan. Pemandangan pecinan yang indah dipenuhi lampion dengan jalanan yang basah dan suasana sejuk usai hujan reda membawa saya pada perenungan bahwa hidup damai berdampingan dengan ragam etnis adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada umat-Nya sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Lagipula, saya tidak melulu melihat orang Tionghoa di sana, orang pribumi bahkan orang Arab juga tak sedikit yang berlalu lalang.
Oleh : Umar Farooq Zafrullah
Sumber :
- Gondodiprodjo, Daradjadi. 2013. Geger Pacinan 1740-1743 Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Toer, Pramoedya Ananta. 2005. Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels. Jakarta: Lentera Dipantara
- Fox, Martin Stuart. 2003. A Short Story of China and Southeast Asia. Tribute, Trade and Influence. Australia: Allen & Unwin
- tirto.id
- Dawis, Aimee. 2010. Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- https://theconversation.com/mengapa-sentimen-negatif-terhadap-etnis-cina-mengakar-kuat-di-indonesia-144673
- Reviews of Religion
Sumber Gambar : voanews.com