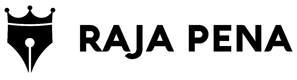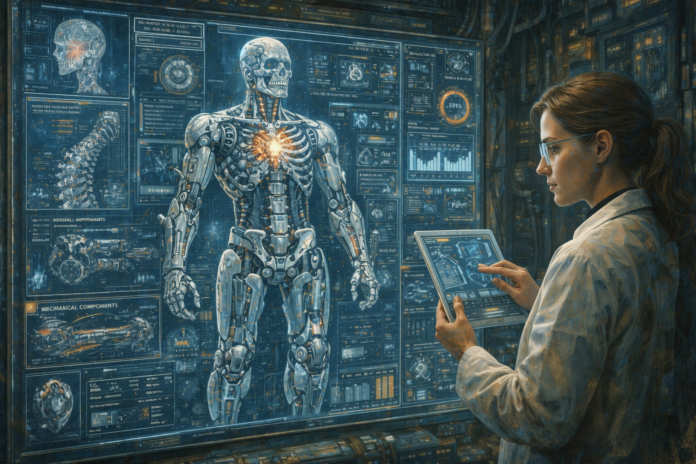Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan sains dan teknologi bergerak dengan kecepatan yang sulit dibayangkan sebelumnya. Di tengah perubahan ini, muncul gagasan transhumanisme, sebuah arus pemikiran yang meyakini bahwa manusia dapat, bahkan seharusnya, melampaui batas biologisnya. Istilah ini diperkenalkan oleh Julian Huxley pada 1957, ketika ia membayangkan tahap evolusi manusia berikutnya yang didorong oleh kemajuan teknologi[1].

Seiring berkembangnya riset ilmiah, gagasan ini memperoleh landasan konseptual melalui berbagai karya akademis. Nick Bostrom, filsuf dari Universitas Oxford, melalui kajiannya tentang peningkatan kapasitas manusia dan masa depan peradaban digital, menekankan bahwa teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan bagian dari proses evolusi yang mampu memperluas kemampuan fisik dan intelektual[2]. Diskusi futuristik mengenai perpanjangan usia biologis dan peningkatan performa tubuh semakin memperkuat gambaran bahwa manusia dapat melampaui kondisi alaminya melalui intervensi teknis[3].
Terlepas dari perdebatan filosofisnya, transhumanisme tidak dapat dilepaskan dari berbagai manfaat teknologi modern. Terapi genetik membuka peluang baru bagi pengobatan penyakit bawaan[4], prostetik cerdas membantu penyandang disabilitas bergerak lebih mandiri[5], dan riset antarmuka otak–komputer menawarkan harapan bagi pemulihan fungsi motorik[6]. Dalam banyak hal, teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan membuka ruang harapan yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Namun sejumlah pemikir mengingatkan bahwa di balik optimisme tersebut terdapat pertanyaan mendasar. Dalam bukunya The Singularity is Near, Ray Kurzweil menggambarkan kemungkinan lahirnya titik ketika kemampuan teknis melampaui batas alami manusia[7]. Pada fase itu, manusia tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga dapat mendefinisikan ulang arti menjadi manusia. Pertanyaan kritis pun muncul: jika tubuh dan pikiran dapat ditingkatkan tanpa batas, apakah makna kemanusiaan tetap sama? Apakah penyempurnaan fisik selalu sejalan dengan penyempurnaan moral? Dan pada titik mana perubahan diri berubah menjadi usaha menciptakan ulang identitas manusia?
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membawa diskursus transhumanisme memasuki wilayah filsafat dan agama, sebab yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar kecanggihan teknologi, tetapi pemahaman tentang hakikat manusia itu sendiri.
Tantangan Filosofis dan Religius terhadap Visi Transhumanisme
Di tengah optimisme terhadap kemajuan teknologi, transhumanisme menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar peningkatan kemampuan tubuh. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa manusia mulai memasuki wilayah yang selama ini dipahami sebagai hak prerogatif Tuhan. Ketika teknologi digunakan untuk menunda kematian, mengubah struktur biologis, atau melampaui batas alamiah manusia, muncul pertanyaan apakah ini benar bentuk perbaikan, atau upaya mengatur ulang tatanan yang diyakini memiliki hikmah ilahi[1]. Dalam banyak ajaran agama, proses menua dan melemah justru dipandang sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bermakna. Selain kritik religius, muncul pula pertanyaan filosofis yang tidak kalah penting. Berbagai tradisi klasik menegaskan bahwa penderitaan memiliki peran dalam membentuk karakter dan kedewasaan moral. Keberanian hanya berarti ketika ada ketakutan, ketabahan lahir dari masa sulit, dan empati tumbuh dari kesadaran akan kerentanan diri. Karena itu, gambaran tentang hidup tanpa tantangan atau tanpa rasa sakit menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas moral tersebut kehilangan dasar tempatnya tumbuh. Manusia mungkin menjadi lebih kuat secara fisik, tetapi dapat kehilangan kedalaman batin yang selama ini memberi makna pada pengalaman hidup.
Nilai Penderitaan dalam Filsafat Klasik dan Ajaran Islam
Pandangan tentang peran penderitaan dalam membentuk manusia telah lama menjadi perhatian para pemikir sejak era Yunani kuno. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles menjelaskan bahwa kebajikan tumbuh melalui pembiasaan menghadapi tantangan. Keberanian, pengendalian diri, dan kearifan bukanlah sifat bawaan, tetapi hasil latihan yang sering kali melibatkan kesulitan. Penderitaan, dalam pengertian ini, menjadi bagian dari proses pembentukan karakter yang kuat[9].
Tradisi Stoa memiliki pandangan serupa. Epictetus dalam Enchiridion menekankan bahwa manusia tidak selalu dapat mengendalikan apa yang menimpanya, tetapi selalu dapat mengendalikan sikap batinnya. Penderitaan menjadi ruang latihan bagi disiplin moral dan ketabahan. Marcus Aurelius dalam Meditations menambahkan bahwa kesulitan merupakan bagian dari tatanan alam, dan manusia bertumbuh ketika memilih meresponsnya dengan kejernihan dan keteguhan hati[10].
Ajaran Islam juga menempatkan penderitaan sebagai bagian dari proses moral dan spiritual. Al-Qur’an menyatakan, “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Asy-Syarh [94]: 6), serta mengingatkan bahwa manusia tidak akan dibiarkan mengaku beriman tanpa diuji (QS. Al-‘Ankabut [29]: 2).
Kisah Nabi Ayyub menjadi contoh paling kuat tentang makna penderitaan dalam Islam. Dalam cobaan berupa penyakit, kehilangan, dan kesulitan hidup, beliau tetap menjaga keteguhan iman. Al-Qur’an menggambarkannya sebagai hamba yang sabar dan selalu kembali kepada Allah (QS. Shad [38]: 44). Pelajaran utamanya bukan pemuliaan terhadap rasa sakit, melainkan bagaimana manusia menemukan kualitas terbaik dirinya melalui ujian yang berat.
Kontroversi antara Transhumanisme dan Nilai Penderitaan
Penting untuk dipahami bahwa perbedaan antara transhumanisme dan ajaran agama tidak terletak pada upaya mengobati penyakit atau memulihkan kesehatan. Dalam Islam, berobat justru dianjurkan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya” (HR. Abu Dawud, no. 3855). Pesan ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi medis merupakan bagian dari ikhtiar menjaga kehidupan dan meringankan beban manusia.
Persoalan muncul ketika transhumanisme melampaui batas pengobatan dan beralih menjadi upaya mengubah hakikat pengalaman manusia. Dalam visi transhumanisme, penderitaan, rasa sakit, dan kefanaan dipandang sebagai kesalahan biologis yang harus dihilangkan sepenuhnya, bukan sebagai bagian dari kehidupan yang perlu dimaknai.
Pandangan ini bertolak belakang dengan nilai penderitaan dalam filsafat klasik dan ajaran agama. Bagi Aristoteles, kesulitan membentuk karakter. Dalam tradisi Stoa, penderitaan melatih ketabahan. Jika semua rasa sakit dihapus, nilai-nilai seperti keberanian moral dan kesabaran kehilangan ruang untuk berkembang.
Dalam perspektif Islam, penderitaan memiliki dimensi spiritual sebagai proses penyucian jiwa dan penguatan iman. Ketika semua pengalaman sulit dihilangkan melalui intervensi teknis, dimensi spiritual ini pun memudar. Tanpa ujian, kesabaran kehilangan maknanya; tanpa kelemahan, kerendahan hati sulit dipahami.
Intinya, persoalan utama bukan pada teknologi medis, tetapi pada pandangan filosofis transhumanisme yang cenderung melihat kelemahan manusia sebagai cacat yang harus diperbaiki. Berbeda dari ajaran Islam yang memandang sebagian kelemahan sebagai ruang untuk pertumbuhan moral, transhumanisme berisiko menghapus dimensi yang justru memberi kedalaman pada kehidupan manusia.
Akal dan Batas Teknologi
Dalam perdebatan mengenai masa depan manusia, salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara kemampuan teknis dan nilai moral. Pemikiran Ibn Rushd, filsuf besar dari Andalusia, memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana keduanya seharusnya dipadukan. Melalui karya seperti Fasl al-Maqāl dan Tahāfut al-Tahāfut, ia menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak berada dalam posisi berlawanan, tetapi bekerja saling melengkapi dalam menjelaskan realitas[11].
Bagi Ibn Rushd, akal merupakan anugerah yang memungkinkan manusia mempelajari hukum alam dan mengembangkan sains. Karena itu, penelitian dan inovasi teknologi dipandang sebagai bagian dari tugas manusia memakmurkan dunia. Namun ia juga menekankan bahwa akal harus bergerak dalam batas etika yang dituntun oleh wahyu. Sains dapat menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, tetapi wahyu memberi arah tentang tujuan tindakan tersebut.
Pandangan ini menjadi sangat relevan ketika menilai ambisi transhumanisme. Selama teknologi digunakan untuk mengobati dan memulihkan, arah tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan. Namun ketika teknologi diarahkan untuk meniadakan seluruh bentuk kelemahan manusia atau mendorong manusia melampaui kodratnya sebagai makhluk yang memiliki rasa sakit dan kefanaan, muncul pertanyaan apakah perkembangan tersebut masih berada dalam koridor nilai, atau justru mulai menggeser makna dasar tentang manusia. Pemikiran Ibn Rushd mengingatkan bahwa kemajuan teknologi memerlukan panduan moral. Sains membuka apa yang mungkin dicapai, tetapi agama menjaga agar pencapaian itu tetap berada dalam tujuan yang benar. Dalam perbincangan tentang transhumanisme, keseimbangan inilah yang menentukan apakah teknologi menjadi sarana kebaikan, atau justru membuat manusia kehilangan orientasi spiritualnya.
Penutup
Transhumanisme sering dibayangkan sebagai pintu menuju berbagai kemungkinan baru dalam kehidupan manusia. Namun di balik berbagai inovasi yang ditawarkan, terdapat pertanyaan mendasar tentang bagaimana perubahan itu akan memengaruhi cara kita memahami diri sendiri. Keinginan untuk hidup lebih lama, menjalani hidup tanpa rasa sakit, atau melemahkan batas-batas biologis memang menarik, tetapi setiap dorongan semacam itu perlu dilihat tidak hanya dari sisi teknologinya, melainkan juga dari nilai yang menyertai proses tersebut.
Teknologi yang membantu meringankan beban hidup manusia tentu layak disyukuri. Namun ketika teknologi diarahkan untuk menghapus seluruh keterbatasan yang justru membentuk karakter dan kedalaman spiritual, kita perlu bertanya: Apakah yang kita kejar sesungguhnya? Kesehatan, atau ketidakterbatasan? Dan apakah ketidakterbatasan itu membawa kebaikan, atau justru menjauhkan kita dari makna hidup yang sejati.
Gagasan tentang kehidupan tanpa rasa sakit terdengar ideal, Namun tanpa tantangan yang melatih kesabaran, ketabahan, dan perenungan, apa hakikat pendewasaan diri? Jika semua rintangan dihilangkan, mampukah kita masih menemukan nilai-nilai moral yang selama ini lahir dari pergulatan menghadapi kesulitan?
Kemajuan teknologi tidak mungkin dihentikan, tetapi arah perkembangannya tetap menjadi pilihan. Masa depan yang patut diperjuangkan bukanlah masa depan yang memutus manusia dari kemanusiaannya, melainkan masa depan di mana teknologi mendukung pertumbuhan moral dan tujuan penciptaan manusia. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya “apa yang dapat dilakukan teknologi, tetapi ke mana ia seharusnya membawa manusia?.”
Oleh: Danish Ahmad
Catatan Kaki:
[1] Julian Huxley, New Bottles for New Wine (London: Chatto & Windus, 1957).
[2] Nick Bostrom, “A History of Transhumanist Thought,” Journal of Evolution and Technology 14, no. 1 (2005).
[3] Nick Bostrom and Anders Sandberg, “The Wisdom of Nature: An Evolutionary Heuristic for Human Enhancement,” Philosophy & Technology 24, no. 3 (2011).
[4] Jennifer A. Doudna and Samuel H. Sternberg, A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017).
[5] Hugh Herr, “The Biomechanics of Bionic Limbs,” Scientific American 321, no. 2 (2019).
[6] Leigh R. Hochberg et al., “Neuronal Ensemble Control of Prosthetic Devices by a Human with Tetraplegia,” Nature 442 (2006).
[7] Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (New York: Viking, 2005).
[8] Adnan Aslan, Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy: The Thought of John Hick and Seyyed Hossein Nasr (London: Routledge, 1999).
[9] Aristotle, The Nicomachean Ethics, trans. Lesley Brown (Oxford: Oxford University Press, 2009)
[10] Epictetus, Enchiridion, trans. Nicholas P. White (Indianapolis: Hackett Publishing, 1983); Marcus Aurelius, Meditations, trans. Gregory Hays (New York: Modern Library, 2002).
[11] Oliver Leaman, Averroes and His Philosoph, 1st ed. (London: Routledge, 2013);