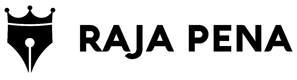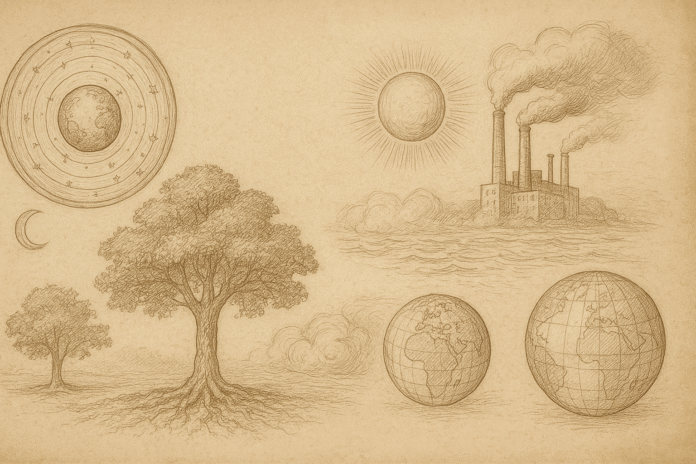
Pendahuluan
Krisis iklim saat ini bukan hanya tantangan ilmiah dan teknologi, tetapi juga tantangan moral dan spiritual. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam Sixth Assessment Report (2023)1, suhu permukaan bumi telah meningkat sekitar 1.1°C sejak era pra- industri, permukaan laut naik 3.3 mm per tahun, dan emisi gas rumah kaca mencapai lebih dari 36 GtCO₂ per tahun. Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan keterbatasan jika tidak disertai transformasi cara pandang manusia terhadap alam. Maka dari itu, artikel ini mencoba membingkai ulang relasi manusia dengan alam semesta melalui lensa kosmologi Islam dan pendekatan ilmiah dengan mengeksplorasi konsep amanah dalam dimensi ontologis dan etisnya, mengaitkannya dengan tatanan kosmos dalam kosmologi Islam.
Krisis Ekologis dan Spiritualitas
Dalam khazanah Islam, alam bukanlah entitas mati yang dapat dieksploitasi, melainkan bagian dari tatanan kosmik yang memiliki kesadaran, keteraturan, dan fungsi ibadah. Manusia dalam halini bukan sebagai pemilik absolut, melainkan sebagai khalifah yang mengemban amanah (QS. Al- Ahzab:72).
Seyyed Hossein Nasr dalam karyanya The Encounter of Man and Nature (1968)2 menyatakan bahwa krisis ekologi modern berakar pada “pembunuhan spiritual terhadap alam.” Dalam pandangannya, alam telah direduksi menjadi objek mekanistik tanpa jiwa, akibat dari dominasi paradigma Cartesian-Newtonian dalam sains modern. Alam tidak lagi dilihat sebagai ciptaan suci, melainkan sebagai sumber daya yang tersedia untuk dieksploitasi secara tak terbatas (res extensa)1.
Nasr (1968)2 menyebut fenomena ini sebagai desacralization of nature, yakni penghilangan dimensi transenden dari alam. Dalam kerangka modernitas, hubungan manusia-alam berubah dari koeksistensi menjadi dominasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada degradasi ekologis, tetapi juga menciptakan kekosongan spiritual dalam diri manusia.
Dalam perspektif Islam, alam adalah ciptaan Allah yang memiliki fungsi ibadah dan kesadaran spiritual. QS. Al-Isra’:44 menyatakan bahwa “Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah.” Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh kosmos terlibat dalam kesadaran ketuhanan. Oleh karena itu, merusak alam berarti juga mengganggu tatanan ibadah universal.
Lebih jauh, paradigma dominan dalam tradisi Barat modern, terutama setelah abad Pencerahan, adalah anthropocentrism— yakni pandangan bahwa manusia adalah pusat dari segala nilai dan tujuan di alam semesta. Dalam konteks ini, makhluk non-
manusia, termasuk hewan, tumbuhan, dan elemen ekologis lainnya, hanya dianggap bernilaisejauh mereka berguna bagi manusia. Pandangan ini telah mendorong eksploitasi alam besar-besaran dan peminggiran hak-hak makhluk lainnya.
Sebaliknya, dalam kosmologi Islam, seluruh makhluk adalah bagian dari tatanan ibadah kosmik. Alam semesta tidak diciptakan semata untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi untuk menampakkan keagungan Tuhan. Ayat-ayat Qur’an seperti QS. Al- Hajj:18 dan QS. An-Nur:41 menyatakan bahwa seluruh makhluk, termasuk burung, pepohonan, dan bintang-bintang, bertahmid dan bersujud kepada Allah sesuai fitrahnya.
Dengan demikian, etika Islam bersifat biocentric3bahkantheocentric4, menempatkan seluruh makhluk sebagai subjek etis yang wajib dihormati. Dalam kerangka ini, hak ekologis makhluk non- manusia (QS 6:38)5 bersumber dari relasinya dengan Tuhan, bukan antroposentrisme
utilitarian6. Konsekuensi etisnya adalah larangan isrāf (pemborosan, QS 7:31)7 dan kewajiban ‘adl (keadilan ekologis, QS 55:7- 9). Pendekatan ini sejalan dengan Earth Jurisprudence (Cullinan 2011)8 namun memiliki otoritas normatif yang lebih kuat melalui institusi fatwa dan fikih lingkungan.
Kosmologi Islam dan Tatanan Alam
Dalam kosmologi Islam, tatanan alam semesta merupakan manifestasi dari kehendak dan ilmu Tuhan. Konsep tanzil (penurunan) tidak hanya berlaku pada wahyu, tetapi juga pada penciptaan alam sebagai “ayat-ayat kauniyah9.” Para filsuf Muslim klasik seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina memandang alam sebagai realitas hierarkis yang tersusun secara logis dan rasional, bergerak dariTuhan Yang Maha Esa menuju bentuk-bentuk yang lebih rendah melalui proses emanasi.
Dalam kosmologi emanatif Al-Farabi10, alam semesta merupakan pancaran (fayd) dari Akal Pertama, dan setiap tingkatan realitas memancarkan keteraturan dan tujuan. Alam bukan entitasotonom, melainkan bagian dari hierarki intelek yang tersusun secara harmonis. Bagi Al-Farabi, memahami alam berarti memahami akal dan hukum-hukum universal yang ditanamkan oleh Tuhan. Karena itu, merusak keteraturan alam berarti melawan prinsip rasionalitas dan keteraturan yang menjadi dasar kosmos. Alam adalah media untuk mencapai kebahagiaan (sa‘ādah), dan manusia sebagai makhluk rasional memiliki tanggung jawab untuk menjaga tatanan tersebutsebagai bagian dari pembangunan jiwa dan masyarakat.
Selain itu, Ibn Sina menyatakan bahwa alam adalah cermin dari hikmah ilahi dan memiliki keteraturan bawaan yang mencerminkan keteraturan Tuhan11. Sedangkan, Ibn ‘Arabi
melalui doktrin wahdat al-wujud12, melihat seluruh eksistensi sebagai manifestasi dari nama-nama Tuhan; maka merusak makhluk berarti juga mengganggu manifestasi Ilahi itu sendiri.
Dalam QS. Ar-Rahman:7-9 ditegaskan konsep mizan (keseimbangan): “Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan mizan (timbangan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang mizan itu.” Ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan merupakan hukum universal yang mengatur seluruh ciptaan.
Secara ilmiah, konsep ini paralel dengan prinsip homeostasis13 dan keseimbangan ekosistem dalam ilmu lingkungan. Ketika manusia merusak sistem penyangga kehidupan seperti hutan, lahan basah, dan lapisan ozon, maka stabilitas ekologis pun terganggu.Prinsipkeberlanjutan menekankan pentingnya menjaga daya dukung bumi agar tidak melampaui batas ambang.
Amanah dan Khalifah dalam Etika Ekologis
Konsep amanah merupakan pusat dari relasi manusia dengan lingkungan dalam Islam. QS. Al-Ahzab:72 menyatakan bahwa amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, namun mereka menolaknya karena berat, dan manusia menerimanya. Ini bukan hanya tentang kehormatan, tetapi juga tanggung jawab eksistensial.
Sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah:30), manusia diberi kapasitas akal dan kehendak bebas untuk mengelola bumi. Namun kekhalifahan ini bukan berarti dominasi, melainkan pengelolaan yang adil, proporsional, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif kontemporer, ini dapat diterjemahkan dalam kerangka teknologi ramah lingkungan, sistem energi terbarukan, serta prinsip efisiensi dan sirkularitas dalam desain produk.
Prinsip daur hidup yang digunakan dalam ilmu biologi dan lingkungan sejalan dengan pandangan Islam tentang keberlanjutan dan tanggung jawab antargenerasi. Dalam hal ini, etika Islam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.
Islam, Fasād, dan Keadilan Ekologis
QS. Ar-Rum:41 menyatakan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Ayat ini menekankan hubungan kausal antara kerusakan ekologis dan tindakan manusia.
Kata fasād dalam konteks ini bukan hanya degradasi fisik, tetapi juga kerusakan moral dan spiritual.Dalam sains lingkungan, hal ini tercermin dalam degradasi biodiversitas, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2019)14 mencatat bahwa sekitar 1 juta spesies terancam punah, dan75% permukaan daratan telah dimodifikasi secara signifikan oleh aktivitas manusia.
Konsep mizan dan larangan fasād memberikan dasar bagi keadilan ekologis dalam Islam. Ini mencakup hak generasi mendatang untuk mewarisi bumi yang layak huni, serta hak makhlukhidup lainnya untuk eksis dalam keseimbangan.
Penutup
Krisis ekologi mencerminkan hilangnya spiritualitas dan etika dalam relasi manusia dengan alam. Dalam kosmologi Islam, manusia bukan penguasa mutlak, melainkan penjaga amanahyang meneladani sifat Tuhan dalam memelihara ciptaan. Integrasi nilai Qur’ani seperti amanah,mizan, dan larangan fasād dengan pendekatan ilmiah menghadirkan etika ekologis yang menyeluruh. Amanah menjadi panggilan eksistensial untuk menjaga keseimbangan kosmos sebagai wujud pengabdian kepada Sang Pencipta.
Oleh: Danish Ahmad
Catatan kaki:
1 IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2023
2 Nasr, Seyyed Hossein. The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man. George Allen & Unwin, 1968.
3 Pandangan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar alat untuk kepentingan manusia.
— Paul W. Taylor, Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics (Princeton: Princeton University Press, 1986).
4 Pandangan bahwa Tuhan sebagai pusat realitas, dan nilai alam diturunkan dari hubungannya dengan Yang Ilahi.—Seyyed Hossein Nasr, The Encounter of Man and Nature (London: Allen & Unwin, 1968)
5 “Tidak ada satupun makhluk melata di bumi maupun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecualimerupakan umat-umat seperti manusia.” Hal ini menegaskan kesetaraan ontologis seluruh makhluk dalam tatananciptaan.
6 Pandangan etika yang menilai alam semata berdasarkan manfaat instrumental bagi kepentingan manusia, mengabaikan nilai intrinsik ekosistem.” Lihat John Stuart Mill, Utilitarianism (1863), Chap. 2.
7 Dasar fikih larangan pemborosan sumberdaya alam. “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”
8 “Filsafat hukum yang mengakui hak-hak alam sebagai subjek hukum independen dari nilai manusia.” LihatCullinan, Cormac, ‘Earth Jurisprudence’, in Lavanya Rajamani, and Jacqueline Peel (eds), The Oxford Handbook of International Environmental Law, 2nd edn, Oxford Handbooks (2021; online edn, Oxford Academic, 8 Dec. 2021),
9 Ayat-ayat kauniyah: Tanda-tanda kebesaran Allah yang termanifestasi dalam fenomena alam, berfungsi sebagaibukti keesaan dan kekuasaan-Nya (QS 3:190-191, 41:53). Istilah ini dibedakan dari ayat-ayat qur’aniyyah (wahyutekstual).
10 Lihat Al-Fārābī, The Political Regime (Al-Siyāsah al-Madaniyyah), diterjemahkan oleh Fauzi Najjar, dalamMedieval Political Philosophy, ed. Ralph Lerner dan Muhsin Mahdi (Ithaca: Cornell University Press, 1963); juga Thérèse-Anne Druart, “Al-Farabi,” dalam History of Islamic Philosophy, ed. Nasr & Leaman (London: Routledge, 1996)
11 Avicenna, The Metaphysics of The Healing, diterjemahkan oleh Michael E. Marmura. Brigham Young University Press, 2005.
12 Lihat Ibn ‘Arabi, Futūḥāt al-Makkiyya; William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination (Albany: SUNY Press, 1989); bandingkan pula Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts (Berkeley: University of California Press, 1984).
13 “Mekanisme biologis organisme untuk mempertahankan keseimbangan internal (seperti suhu tubuh, pH, ataukadar glukosa) melalui proses regulasi otomatis, meskipun menghadapi perubahan lingkungan eksternal.”
— Lihat Claude Bernard, Introduction to the Study of Experimental Medicine (1865).
ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.
14 IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio, H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A.Chan,
Referensi:
L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and
C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.
Image:
Generate ai ChatGPT, 13 Oktober 2025